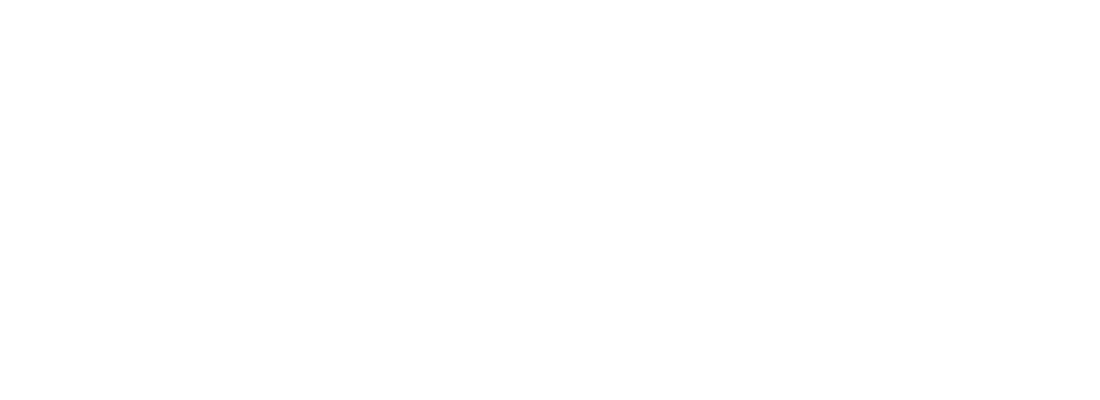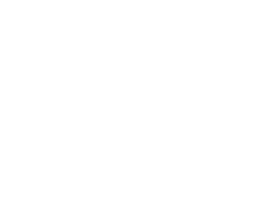Membaca buku Pak Djon, “Aku Datang, Aku Lapar, Aku Pulang” yang berkisah tentang kedekatan relasinya dengan Affandi, membawa kita pada gambaran yang lebih riil atas seniman yang menjadi legenda dalam sejarah seni Indonesia. Pak Djon menggambarkan Affandi sebagai sosok yang unik di tengah kehidupan kosmopolitannya. Ya, memang tidak bisa disangkal bahwa Affandi merupakan pelopor dalam masuknya Indonesia dalam peta seni internasional, terutama pada tahun 1950an ketika ia menggelar pameran besar di New York dan terlibat dalam perhelatan penting seperti Venice Biennale dan Sao Paulo Biennale.
Menelusuri kembali gagasan internasionalisme, pada 1950an ini, untuk bangsa yang masih belia seperti Indonesia, ada banyak temuan menarik yang menunjukkan bagaimana politisi, diplomat, kaum intelektual dan seniman pada masa itu telah bergerak menjadi bagian dari arus dunia. Meskipun terpecah ideologi, pada masa ini justru kita mewarisi banyak perdebatan bermutu tentang identitas ke-Indonesia-an, dan sekaligus kita melihat bagaimana Negara mengambil peran dalam merespon dinamika internasional dan politik kebudayaan di tingkat lokal. Soekarno, Presiden Pertama Indonesia, membuka misi-misi diplomatik di seantero dunia, dan ia sendiri melakukan perjalanan kenegaraan secara rutin ke luar negeri, misalnya ke Amerika Serikat dan terutama ke Negara blok sosialis seperti Cina, Jepang, Timur Tengah dan Afrika. Jennifer Lindsay menyebut dalam pengantar buku “Ahli Waris Budaya Dunia”, mimpi Soekarno, yang juga terefleksi dalam pemikiran-pemikiran intelektual pada masa itu, menjadi Indonesia berarti menjadi modern. Ada rasa girang terhadap “kebaruan” menjadi “terlahir” sebagai bangsa dan warga baru. Kata-kata “baru”, “lahir” dan “modern” merembes ke tulisan-tulisan periode tersebut.
Secara umum, penelitian mengenai bagaimana Indonesia dipanggungkan dalam dunia seni internasional ini sendiri banyak terinspirasi oleh penelitian Jeniffer Lindsay dan kawan-kawan, yang berfokus pada periode 1950 – 1960. Buku “Ahli Waris Budaya Dunia” memberikan gambaran penting bagaimana Negara menempatkan kebudayaan sebagai alat dasar untuk memahami Indonesia pada zaman itu. Salah satu ilustrasi dari nilai penting kebudayaan adalah bagaimana di tengah perjuangan dan pergolakan untuk mempertahankan kemerdekaan pada 1948, di mana kekuasaan Republik masih sebatas di beberapa bagian Sumatera dan Jawa, pemerintah menggelar Kongres Kebudayaan yang pertama di Magelang. Lindsay kemudian mencatat bahwa pada akhirnya, sebagaian besar penelitian tentang kebudayaan pada masa 1950 hingga 1960an banyak berfokus pada sastra atau sebagian kecil mengenai film, yang terutama menyajikan perdebatan-perdebatan tentang Lekra dan Manikebu, sehingga jarang memberi ruang pada fenomena budaya lain di masa itu.
Menggabungkan catatan-catatan personal tentang kehidupan para seniman besar dengan penelitian ilmiah dari para sarjana seperti Jeniffer Lindsay memberi gambaran menarik tentang dinamika menjadi Indonesia di mata para pekerja seni, dari satu periode ke periode yang lain, terutama untuk melihat siapa yang menjadi agen dari internasionalisasi seni. Setelah 1965, setelah rezim Soekarno jatuh dan tampak bahwa Soeharto tidak memberi ruang signifikan pada diplomasi kebudayaan, siapa yang menjadi aktor dalam upaya memanggungkan Indonesia? Apakah seniman sebagai individu, sebagai yang tercatat pada Affandi, merupakan agen yang signifikan pada masa Orde Baru? Jika Soekarno tertarik pada gagasan mengenai Indonesia sebagai bagian dari warga dunia, maka gagasan apa yang mendasari kebijakan politik kebudayaan pada masa sesudahnya? Adakah agen-agen lain yang berperan dalam memanggungkan Indonesia di panggung internasional ketika peran Negara tidak dominan? Apakah narasi dan ideologi yang mendasari para agen ini berseberangan atau beriringan dengan ideologi kebudayaan pasca Orde Lama? [bersambung]
Selengkapnya di Agensi dan Internasionalisme: Memanggungkan Indonesia di Peta Seni Rupa Global oleh Alia Swastika
Sumber tulisan: https://independent.academia.edu/AliaSwastika