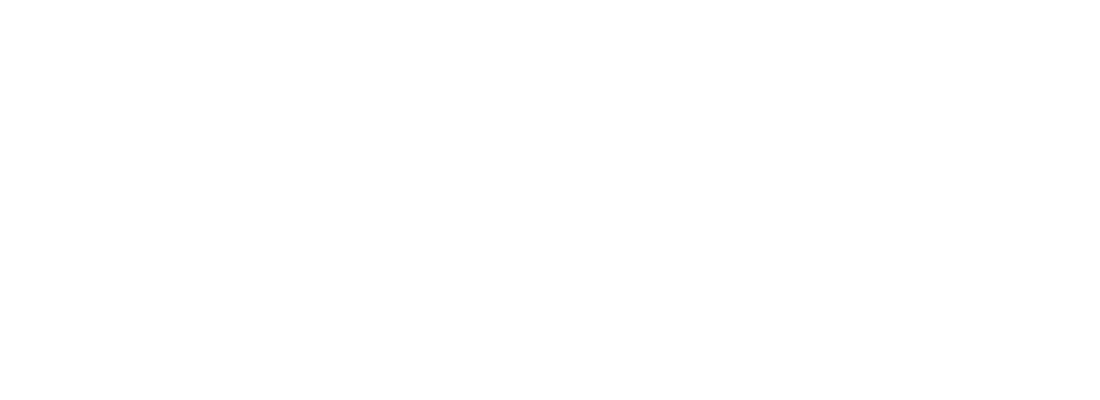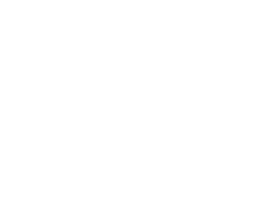Oleh: Hikmat Darmawan
(Kurator dan Direktur Kreatif Pabrikultur, Anggota Koalisi Seni)
Versi pendek tulisan ini dimuat di Harian Kompas pada 18 Februari 2020, sebagai tanggapan untuk opini Radhar Panca Dahana
Apakah kebudayaan di sebuah masyarakat yang masih hidup bisa mati? Radhar Panca Dahana, dalam tulisan bombastis di Kompas, 21 Januari 2020, menyebut bahwa Indonesia saat ini mengalami “sakratul maut seni-budaya”. Radhar menyatakan bahwa kebudayaan mengalami “humilisasi” dan “asasinasi” oleh Negara/rezim Jokowi.
Radhar lanjut merenceng pendapat bahwa sejak Orde Baru hingga era SBY, tak ada yang memahami kebudayaan di dalam pemerintahan. Ia menyebut bahkan era Gus Dur yang mantan ketua Dewan Kesenian Jakarta, kebudayaan dan seni “tidak mendapat porsi yang cukup”. Hingga era Jokowi, menurut Radhar, Negara kerjanya menghina kebudayaan. Malah, untuk periode kedua Jokowi ini, Radhar melancarkan serangkaian tuduhan serius: “(N)apas-napas dari kebudayaan… sedang diputus dengan telengas”, “pembunuhan (terhadap kebudayaan)”, dan bahkan menyaran bahwa pemerintah kini adalah otoriter seperti pemerintahan komunis.
Ada tiga basis utama rangkaian tuduhan Radhar bahwa pemerintah sedang menghina, membunuh, dan otoriter pada kebudayaan: perubahan nomenklatura dan struktur kementerian pendidian dan kebudayaan yang menghapus direktorat kesenian; kasus revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) yang dianggap sebagai “komersialisasi” TIM; dan asumsi bahwa biaya kebudayaan adalah beban bagi anggaran Negara atau Pemda.
Ketiga basis itu sesungguhnya tak melalui cek dan cek-ulang yang memadai. Tapi, sebelum ke soal itu, saya ulas dulu bahwa tuduhan-tuduhan Radhar telah bermasalah sejak di taraf kerangka pikir.
Sikap nihilistik yang tidak memajukan
Premis bahwa kebudayaan suatu masyarakat bisa mati, sekarat, di dalam sebuah masyarakat yang masih hidup sungguh problematik dalam berbagai segi. Apakah artinya kebudayaan hidup secara terpisah dari masyarakatnya –berada di luar masayarakat? Hal ini sungguh aneh buat saya. Kita bisa bicara tentang tradisi atau bahasa yang mati, misalnya: sebutlah bahasa Aramaik atau tradisi perbudakan yang tak lagi digunakan –tapi, apakah kita bisa lantas mengatakan bahwa kebudayaan masyarakat tempat bahasa Aramaik atau tradisi perbudakan pernah hidup itu sebagai telah mati?
Dalam pemahaman ini, sesama manusia bisa tetap berpakaian, memilih makanan, berbicara satu sama lain, membaca, menggunakan laptop, bekerja, berpikir, menghias dinding kamar dengan poster, berjual beli secara online, sembari dikatakan bahwa kebudayaannya “sakratul maut”, “mati”, “dibunuh”. Radhar menulis: “…apakah hingga kebudayaan dimakamkan, …bangsa jadi mayat, atau zombi yang hidup hanya untuk menciptakan keburukan dan kebobrokan?”
Dalam pertanyaan retoris itu, tergambar imajinasi Radhar bahwa kebudayaan di sebuah masyarakat bisa mati, sementara masyarakatnya yang masih hidup dianggap sebagai “zombi”. Imajinasi demikian tak pelak lahir dari kerangka berpikir yang menganggap kebudayaan sebagai sebuah bentuk yang hanya bisa diproduksi dengan cara tertentu. Apabila tak diproduksi dengan cara tertentu itu, kebudayaan dianggap mati, dan masyarakat yang masih hidup itu dianggap “zombi”.
Di sini, kita bisa mempertanyakan apa “cara tertentu” itu, sekaligus mempertanyakan siapa yang memberi batas apa “cara tertentu” itu dan menilai “cara tertentu” apakah yang valid sebagai, katakanlah, “roh” hidup sebuah kebudayaan.
Sebelum lanjut mempertanyakan, saya tawarkan pemahaman apa itu “kebudayaan” yang saya anut. Saya percaya konsep kebudayaan yang didukung Cliford Geertz (Tafsir Kebudayaan, terj. Kanisius, 1992): ia adalah jaringan-jaringan makna. Konsep ini diambil Geertz dari Max Weber, yang menyatakan bahwa manusia adalah “seekor binatang yang bergantung pada jaringan-jaringan makna yang ditenunnya sendiri”. Ini berarti, kata Geertz, konsep kebudayaan yang semiotis.
Konsep kebudayaan ini menerima bahwa setiap tindakan manusia pada sesama adalah lakon penciptaan makna melalui tindakan pertukaran simbol. Jelasnya, setiap kali manusia berkomunikasi dengan sesama, ia sedang menenun makna, dan kebudayaan pun tercipta, hidup. “Kebudayaan adalah komunikasi, dan komunikasi adalah kebudayaan”, begitu ungkapan dari Edward T. Hall (The Silent Language, 1959). Dengan demikian, saya percaya kebudayaan selalu hidup dalam sebuah masyarakat yang masih melakoni drama pertukaran simbol, berkomunikasi, dari hari ke hari.
Dalam konteks itu, walau percaya bahwa ada persoalan kualitas kebudayaan, saya menganggap keliru sikap nihilistik bahwa jika kualitas sebuah kebudayaan itu (dianggap) buruk adalah berarti sebuah kematian kebudayaan. Saya sebut sikap demikian nihilistik, karena dengan menganggap sebuah kebudayaan mati hanya karena tidak sesuai dengan standar kualitas kebudayaan seseorang atau suatu kelompok, maka peluang pemajuan kebudayaan pun ditutup atau dinihilkan.
Sikap itu mengandung sebuah elitisme kebudayaan. Sedangkan elitisme kebudayaan sudah tak masuk akal lagi dalam dunia yang semakin terbuka kini. Elitisme demikian juga memperbesar titik-buta dalam memandang dinamika kebudayaan Indonesia saat ini.
Kebudayaan yang luput dari Sang Budayawan
Elitisme Radhar segera terbaca dari artikel opininya itu, ketika berulang ia menegaskan bahwa presiden demi presiden, pemerintahan demi pemerintahan, dari pusat hingga daerah, tak paham apa arti penting kebudayaan. Sikap ini meluputkan Radhar dari capaian penting dalam relasi Negara dan kebudayaan: UU no. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
Istilah “Pemajuan Kebudayaan” merujuk pada UUD 1945 pasal 32, yang menyebutkan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.” Hal ini boleh dibilang revolusioner karena dua hal.
Pertama, selama lebih dari 10 tahun, DPR mengajukan RUU Kebudayaan dengan semangat “mengatur” dan menguatkan “kebudayaan nasional” untuk menangkal “ancaman budaya asing”. Semangatnya masihlah sama dengan semangat Orde Baru (Orba) memperlakukan kebudayaan, yakni pengendalian Negara atas kebudayaan, dan pada gilirannya adalah kendali total Negara atas warga. Dengan kembali pada pasal 32 UUD 1945, semangat itu dijungkir menjadi semangat fasilitasi. Negara jadi fasilitator pemajuan kebudayaan. Bahkan, salah satu amanat dari UU no. 5/2017 itu adalah menjadikan strategi kebudayaan nasional sebagai landasan pembangunan nasional.
Kedua, persoalan kebudayaan dan kesenian sejak Orba selalu berparadigma “pelestarian” (terhadap seni dan budaya tradisional) yang mewujud pada politik anggaran yang membatasi fasilitasi Negara pada arena pelestarian. Kesenian modern dan kontemporer selalu wagu, kesulitan mencari posisi, di dalam politik anggaran demikian. UU no. 5/2017 memang masih menggunakan istilah umum dan rentan terhadap tafsir karet yakni “Perlindungan”, “Pengembangan”, “Pemanfaatan”, dan “Pembinaan” kebudayaan. Tapi, sejauh terbaca dari sosialiasi UU Pemajuan Budaya oleh Dirjen Kebudayaan selama ini, setidaknya paradigma politik anggaran sebatas “Pelestarian” telah diganti oleh empat aspek “Pemajuan” tersebut.
Apakah kedua hal itu hanya normatif? Pada Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) 2018, Hilmar Farid sebagai Dirjen Kebudayaan, mencanang hasil berupa perumusan Strategi Kebudayaan Indonesia yang akan berlaku selama 20 tahun ke depan. Yang perlu dicatat: basis strategi kebudayaan itu adalah data tentang masalah dan situasi seni-budaya yang dikumpulkan secara massif selama 2018 dari lebih 514 kabupaten/kota, 34 propinsi. Artinya, strategi ini disusun secara bottom up, menyerap kenyataan seni-budaya di akar rumput, sembari tetap dijaga dalam perumusan akhirnya oleh sekumpulan ahli dan ilmuwan berbagai bidang.
Proses perumusan demikian, walau mungkin masih rumpang secara metodologi, lebih otentik daripada proses perumusan strategi kebudayaan oleh para elite kebudayaan berstatus “dewa” (tepatnya, didewakan) yang bersifat top down. Dan justru moda top down itu yang dilakukan oleh Radhar Panca Dahana pada 2018 lewat Mufakat Budaya. Alih-alih menggali aspirasi budaya di tahap warga, Radhar mengumpulkan para ahli dan seniman yang diseleksi secara khusus untuk merumuskan strategi budaya yang dibawa pada presiden Jokowi. Bisa dilacak, berapa kali kelompok Mufakat Budaya pimpinan Radhar mendatangi istana, menyodorkan usulan-usulan tentang bagaimana seharusnya Negara mengelola kebudayaan.
Di tengah kesibukan KKI 2018, saya sempat bertanya secara informal pada Hilmar Farid, bagaimana menyikapi langkah-langkah Mufakat Budaya yang seakan berselisih dengan KKI 2018. Hilmar menganggap, rumusan Mufakat Budaya bagus dan akan jadi salah satu masukan. Di titik itu, saya melihat bahwa Radhar tak bisa menampik bahwa ia berada dalam sebuah ruang kebudayaan yang dinamis, yang justru menjadi dinamis karena tak lagi percaya pada dewa-dewa kebudayaan yang maha-tahu dan maha-benar soal kebudayaan.
Luputnya Radhar membaca dinamika itu juga berkelindan dengan kesan bahwa Radhar, dalam khutbah-khutbahnya tentang kematian budaya, tampak gagal memperhitungkan situasi de facto kebudayaan kontemporer kita yang tak melulu berisi toxic politic di media sosial. Sekadar menggurat sketsa, perhatikanlah dua hal: (1) kiprah para seniman Indonesia di ajang internasional sepanjang, taruhlah, lima tahun belakangan; (2) kiprah dunia seni Indonesia di kota-kota Indonesia yang bergerak terus menyiasati keterbatasan ruang seni di setiap kota.
Sesuatu yang sangat penting sedang terjadi: seniman kita mulai lincah menyumbang percakapan kultural di tingkat dunia. Paling penting saat ini, a.l.: kolektif Ruang Rupa pimpinan Ade Darmawan terpilih tahun lalu sebagai direktur artistik Documenta, ajang senirupa terbesar di Eropa, 2022. Tak kurang penting, karya FX Harsono, Writing in the Rain, tampil di Time Square New York selama Januari 2018. Lalu, selama berbulan-bulan di 2019, Yudi Tajudin (Teater Garasi) menyusun dan mementaskan teater lintas-Asia di Tokyo dan Flores. Novel Eka Kurniawan masuk nominasi Man-Booker International Prize 2016. Tahun lalu, buku Intan Paramdhita dan Feby Indirani diterjemah di Eropa. Trilogi Jailolo karya Eko Supriyanto keliling Eropa pada 2017. Garin Nugroho berkeliling Eropa dan Australia dengan pemutaran Setan Jawa diiringi komposisi gamelan Rahayu Supanggah. Marlina karya Mouly Surya masuk nominasi Cannes Film Festival.
Itu sebagian saja, dan ada yang difasilitasi Negara, ada juga mendapat dana internasional. Itu adalah puncak gunung es dari dinamika sebuah kebudayaan yang hidup, bukan kebudayaan yang sedang sakratul maut. Jika menelusuri geliat kesenian kontemporer di dalam negeri, geliat itu pun terasa hidup. Berbagai kegiatan komunitas film di Aceh, Purbalingga, Jogjakarta, Lombok, Palu, Makassar, menampak watak DIY dan cinta keras kepala pada sinema. Betapa hidupnya gig dan percakapan di skena musik Indie kita, entah dari mana mau mencatatnya di sini.
Menarik bahwa geliat itu menyimpan watak bersiasat dengan keterbatasan ruang: mereka secara harfiah mencipta ruang-ruang kesenian baru, tanpa menunggu ruang-ruang kesenian disediakan oleh Pusat maupun Negara. Di Jakarta, misalnya, yang terbaru, ada M Bloc, Dia.lo.gue dan Coffeewar di Kemang, Kios Ojo Keos (hasil kerjasama Efek Rumah Kaca dan Pusad Paramadina), dan Gudskul (a.l. dimotori Ruang Rupa dan Serrum) di Jagakarsa. Pergilah ke sana, dan terasa bahwa kehidupan seni-budaya kita justru sedang hidup.
Mengapa budayawan sekaliber Radhar tampak tak terkesan pada geliat kebudayaan terkini itu, dan mendesakkan narasi kesekaratan seni-budaya kita?
Pembunuhan, atau proses negosiasi?
Tiga basis kasus sakratul maut seni-budaya yang diangkat Radhar mengandung misinformasi. Soal perubahan struktur direktorat kebudayaan dan dihapusnya direktorat kesenian telah dibaca keliru oleh Radhar. Saya pribadi menganggap kehadiran Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru sangat problematik. Tapi, Radhar keliru menganggap direktorat baru itu untuk mengganti Direktorat Kesenian. Fungsi Direktorat Kesenian dilebur, agar terjadi koordinasi satu pintu dalam fasilitasi kesenian, dalam kerangka Direktorat Perlindungan Kebudayaan, dan Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan. Istilah “Perlindungan”, “Pengembangan”, dan “Pemanfaatan” (yang sangat ditentang Radhar) adalah mengacu pada UU Pemajuan Kebudayaan.
Basis kedua tulisan Radhar, soal Revitalisasi TIM, mengangkat isu pembangunan hotel berbintang lima, yang sebetulnya hanya isu tanpa bukti konkret. Isu komersialisasi TIM memang penting diangkat mengingat sampai sekarang Jakpro maupun Pemprov DKI belum memapar secara jelas dan rinci model pengelolaan TIM baru nanti apakah memang tak melibatkan seniman, IKJ, serta para pengguna dan pengampu kepentingan TIM selama ini, atau ada model kerjasama lain?
Tapi, Radhar telah berlebihan ketika menggambarkan hal ini sebagai salah satu bukti “titik terendah dalam sejarah peradaban Nusantara”. Yang terjadi dalam soal TIM adalah proses negosiasi, yang berhubungan dengan masalah pelik, “bagaimana membiayai kesenian?”.
Radhar lantas gas pol menyerang penggunaan kata “beban APBD” dalam argumen Pemprov DKI menyertakan BUMD Jakpro dalam Revitalisasi TIM. Bagi Pemprov DKI, biaya Rp. 1,8 triliun untuk membangun TIM baru tak mungkin dibebankan kepada APBD. Jalan keluarnya, biaya dibebankan pada BUMD, dengan konsesi pengelolaan 30 tahun sebatas investasi biaya pembangunan itu “balik modal” bagi BUMD. Di sini, ada wacana tentang bagi-hasil antara Jakpro dengan pembiayaan kesenian di TIM selama 30 tahun. Tapi, sekali lagi, belum jelas bagaimana mekanisme bagi-hasil itu diterapkan.
Radhar dkk. menuntut agar biaya revitalisasi sebesar Rp. 1,8 triliun dan seluruh kegiatan seni di TIM tidak boleh dianggap sebagai “beban”, sepenuhnya dibiayai dari APBD DKI, karena kebudayaan adalah investasi. Menariknya, poin pertama pertimbangan dalam UU Pemajuan Kebudayaan jelas menyebutkan bahwa tujuan Negara memajukan kebudayaan adalah menjadikannya sebagai “investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa”. Tuntutan Radhar malah telah sesuai dengan UU Pemajuan Kebudayaan.
Masalahnya, bagaimanakah mekanisme pemajuan dan investasi di bidang kebudayaan? Jika memang, misalnya, Rp. 1,8 triliun plus biaya kesenian di TIM, harus dari APBD, bagaimana pertanggungjawaban uang rakyat itu di hadapan masalah banjir dan lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, pendidikan, fasilitas umum, dan banyak lagi yang sangat mendesak diatasi?
Tuntutan ini pun saya baca sebagai bagian dari watak elitisme kebudayaan dalam tulisan Radhar. Ia menuntut pengeluaran begitu banyak dari uang rakyat yang dititipkan ke pemprov dan pemerintah pusat untuk kebudayaan, tanpa mau menimbang dasar moral maupun pragmatik mengapa pengeluaran kebudayaan lebih penting daripada pengeluaran lain bagi rakyat. Dan semua ini bertumpu pada asumsi bahwa tak ada satupun kebijakan Negara saat ini adalah untuk mendukung kebudayaan.
Upaya pemprov mencari jalan keluar pragmatik agar Revitalisasi TIM ataupun upaya Kemendikbud mereformasi birokrasi fasilitasi kesenian dan kebudayaan agar lebih sederhana tidak dipandang Radhar sebagai sebuah proses negosiasi untuk pemajuan kebudayaan. Radhar dan kelompok “Save TIM” hanya mau memandang sebelah mata proses negosiasi itu, tampak menampik upaya memahami segi-segi penting politik anggaran pemerintah untuk kebudayaan. Dalam sikap elitisme “paling paham kebudayaan” yang menutup mata pada geliat kebudayaan para pekerja seni saat ini, Radhar menolak langkah-langkah pemajuan kebudayaan yang sedang berjalan.
Dalam konteks itu, menurut saya, yang sedang sakratul maut adalah seni-budaya versi Radhar, bukan seni-budaya di Indonesia senyatanya.