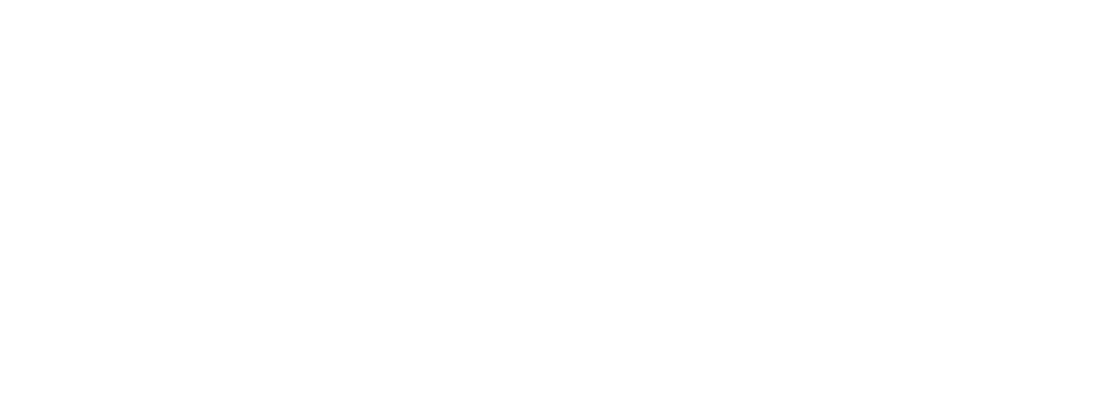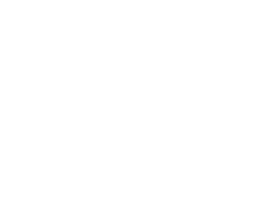Dilema Seni Emansipatoris
Seni dan perubahan sosial adalah salah satu topik paling lawas yang pernah dibicarakan dalam sejarah teori-teori estetika. Tema itu sudah bahkan diperdebatkan pada zaman Yunani Klasik, sekitar 500 – 300 SM. Orang-orang pada masa itu lazimnya beranggapan bahwa karya seni yang baik adalah karya seni yang mengajarkan nilai-nilai moral yang baik. Jadi kesenian dipersepsi secara didaktis sebagai sarana untuk mewujudkan tatanan sosial yang lebih baik. Dalam kerangka didaktis semacam ini, keindahan tidak dapat dievaluasi terpisah dari kegunaan sosial. Suatu karya yang indah mesti juga berguna secara sosial. Di situ, perkara kesenian dan perkara perubahan sosial bukanlah dua hal yang terpisah. Dalam tradisi didaktisis semacam inilah sejarah seni di Eropa berkembang sampai dengan masa Renaisans di abad ke-16.
Konsensus ini dibongkar sejak masa Romantik (abad ke-18 dan 19). Pada masa itu, timbul sejumlah pendapat yang mau melepaskan aspek keindahan karya seni dari seluruh aspek kegunaannya. Karya seni yang baik adalah karya seni yang indah kalau dipersepsi secara ‘tanpa pamrih’ (disinterested). Pemikir estetika seperti Earl of Shaftesbury, Immanuel Kant, Théophile Gautier dan Oscar Wilde dipersatukan oleh kesamaan pendapatnya akan hal ini. Sejak saat itu muncullah dilema khas estetika Modern:
- Tegangan antara keindahan dan kegunaan
- Tegangan antara bentuk dan isi
- Tegangan antara otonomi dan keberpihakan
Beragam pemikiran estetika yang bermuara pada tradisi Modernis akan menekankan keindahan, bentuk dan otonomi seni di atas segalanya. Inilah yang tercermin dalam estetika formalis dan gerakan estetisisme (yang bersemboyan ‘seni untuk seni’). Sementara pemikiran estetika yang berada di luar tradisi Modernis, yakni para penganut estetika realis, sisa-sisa penganut tradisi Klasik dan sebagian penganut estetika Marxis, akan lebih mementingkan kegunaan, isi dan keberpihakan seni. Demikianlah, sejak abad ke-18 tercipta suatu jurang antara seni dan perubahan sosial—sebagian mencoba menjembataninya, sebagian lain justru merayakannya.
Tradisi Modernis dalam estetika menekankan pentingnya evaluasi formal atas karya seni. Hal-hal yang tidak muncul dari ‘kekhasan wahana’ cabang seni terkait dianggap tak perlu disertakan dalam evaluasi estetis. Makna dan acuan mimetik, misalnya, dikesampingkan dari ranah evaluasi seni lukis (Clive Bell dan Clement Greenberg). Lirik dan moral, contoh lainnya, dikesampingkan dari ranah evaluasi seni musik (Eduard Hanslick). Ideologi, pesan dan konteks disingkirkan dari ranah evaluasi kesusastraan (René Wellek dan Austin Warren). Di berbagai cabang seni, aspek-aspek isi, kegunaan dan keberpihakan sang seniman dianggap sebagai elemen-elemen yang asing terhadap karya seni sendiri. Tradisi semacam ini biasanya dibarengi dengan ‘kultus keindahan’, yakni suatu keyakinan yang nyaris religius bahwa karya seni hanya berurusan dengan keindahan. Keyakinan inilah yang dirangkum dalam slogan sejak abad ke-19: seni untuk seni. Tradisi itu juga lazimnya disertai dengan kultus terhadap kemurnian seni dan seniman: karya seni dipandang sebagai hasil kontemplasi murni (tanpa pamrih) dari seorang seniman jenius yang demikian sublim sampai tak bisa dikenali oleh masyarakat biasa. Di sini, ada pemisahan tegas antara ‘benda seni’ dan ‘benda non-seni’ serta antara ‘seniman’ dan ‘orang biasa’.
Sebaliknya, tradisi yang kritis terhadap Modernisme biasanya berangkat dari pengertian Klasik bahwa kesenian sudah selalu jalin-jemalin dengan perkara moral, politik dan seluruh pengaruh ekonomis atau sosio-kultural. Keinsyafan akan keterjalinan itu memungkinkan para estetikawan Modernis untuk mengapresiasi aspek kegunaan, isi dan keberpihakan seni. Di sini, kita dapat memilah dua varian yang sama-sama kritis terhadap Modernisme. Yang pertama bisa kita sebut tradisi ‘anti-Modernis’, yakni para estetikawan yang lebih mementingkan aspek ekstrinsik ketimbang intrinsik dalam evaluasi karya seni. Pemikir seperti Auguste Comte menciutkan peran seni menjadi sekadar sarana untuk mendorong kemajuan moral masyarakat. Sementara birokrat seperti Andrei Zhdanov mewajibkan setiap karya seni untuk menghadirkan penderitaan rakyat pekerja dalam kapitalisme dan kegembiraannya dalam sosialisme serta bertumpu pada mimesis atau penyalinan yang sempurna atas kenyataan indrawi.
Namun, di samping itu, ada varian kritis kedua yang bisa kita sebut tradisi ‘Modernisme dialektis’. Inilah yang mengemuka dalam pemikiran estetika Georg Lukacs, Walter Benjamin, Frederic Jameson dan Terry Eagleton. Pemikiran mereka dipersatukan oleh gagasan bahwa aspek intrinsik dan ekstrinsik dalam setiap karya seni sejatinya saling terhubung dan tak bisa dipisahkan. Bentuk artistik tertentu, seperti misalnya novel, merupakan konsekuensi dari perkembangan sejarah dan karenanya dikondisikan oleh isi artistik. Hubungan timbal-balik yang mempersatukan elemen intrinsik dan ekstrinsik karya seni inilah yang menyebabkan karya seni tetap bisa bermutu secara formal tetapi juga sekaligus mengandung daya emansipatoris.
Apa yang disampaikan sejauh ini masih terbatas pada perkara evaluasi karya seni, belum menyentuh aspek produksi karya seni. Tradisi ‘Modernisme dialektis’ yang berkembang hingga era 1960-an memang berhasil menyelesaikan dilema klasik dalam perkara evaluasi karya seni. Kendati begitu, tradisi ini belum berhasil menyuguhkan suatu pendekatan praktik artistik yang memungkinkan penciptaan karya seni yang dapat dipertanggung-jawabkan secara estetik sekaligus mampu memberikan sumbangan bagi perubahan sosial. Upaya penyelesaian dilema seni pada aras produksi itulah yang berupaya dijawab oleh para pemikir estetika sesudah era 1960-an. Kita dapat memeriksa perkembangan upaya tersebut dengan mengamati pergeseran-pergeseran yang terjadi pada dua ranah sekaligus: pergeseran arti ‘karya seni’ dan pergeseran arti ‘seniman’.
Pergeseran Objek Seni
Akibat kemajuan teknologi, bergeserlah makna ‘karya seni’. Dalam esai klasiknya di tahun 1936, Walter Benjamin telah mencermati gejala lenyapnya ‘aura’ karya seni akibat kemungkinan untuk direproduksi secara mekanis sampai tak hingga. Lenyapnya aura berarti lenyapnya singularitas atau keunikan benda seni. Kemajuan teknologi kamera dan percetakan telah menjalankan desakralisasi atas benda seni. Sebelum adanya teknologi reproduksi citrawi, setiap benda seni seakan mengandung kesan misterius dan suci seperti pusaka yang dikeramatkan dalam kepercayaan religius dikarenakan fakta bahwa benda itu cuma ada satu dan karenanya unik. Kemajuan teknologi reproduksi membuyarkan suasana keramat itu. Berlawanan dengan tafsiran yang lazimnya dijumpai di Indonesia, Benjamin tidak mengartikan hilangnya aura ini sebagai sesuatu yang buruk atau perlu disesali. Justru sebaliknya, ia merayakan itu karena dengan begitulah karya seni bisa diakses oleh masyarakat luas dan dari situ terjadi pensosialan atas pengalaman estetis. Demistifikasi benda seni ini justru memperlihatkan bahwa karya seni bukanlah hasil ritual artistik seorang seniman sublim yang sepenuhnya lain dari kerja ‘masyarakat awam’. Dengan kemungkinannya untuk direproduksi secara mekanis, terbuktilah bahwa kerja seorang seniman bisa disetarakan dengan kerja orang biasa—keduanya sama-sama bertumpu pada keahlian (skill) yang bisa dipelajari dan sama sekali tak ada mistiknya.
Makna karya seni pun bergeser. Karya seni tak lain daripada pencurahan sejumlah tenaga-kerja yang ditubuhkan dalam objek tertentu. Karena itu, esensi karya seni tidak terletak dalam kesubliman benda seni itu sendiri, melainkan dalam sistem pembagian kerja yang memungkinkan produksi benda tersebut. Akar sosial dari definisi karya seni ini ditekankan lebih lanjut oleh para teoretisi seni institusional seperti Arthur Danto dan George Dickie. Mereka berpandangan bahwa sebuah benda menjadi karya seni karena diakui demikian oleh konsensus di kalangan publik seni. Jaringan kolega seniman, kurator, pemilik galeri, kritikus, kolektor—singkatnya semua anggota ‘dunia-seni’ (artworld)—secara bersamaan memberikan pengesahan pada status seni sebuah benda. Dengan begitu, jadi kelihatan bahwa karya seni bukan lagi terjangkar pada bendanya, melainkan pada hubungan sosial yang mensituasikan benda tersebut dan membaptis benda itu jadi karya seni. Inilah yang menjelaskan mengapa urinoir yang dipamerkan Marcel Duchamp atau boks Brillo Warhol menjadi karya seni.
Dari kesadaran yang berkembang bahwa karya seni tak lagi bisa diartikan sebagai benda tetapi lebih terutama sebagai himpunan relasi sosial di balik benda, kemudian muncullah dorongan untuk membaca hubungan antara seni dan perubahan sosial secara baru. Konsepsi lama yang mereduksi pengertian karya seni pada aspek bendawinya telah menghasilkan dilema antara bentuk dan isi, antara aspek intrinsik dan ekstrinsik. Dengan terjadinya pergeseran ke konsepsi baru yang mengartikan karya seni tak lebih dari hubungan sosial yang meliputi sebuah benda, tak ada lagi dikotomi yang bisa dibangun antara aspek intrinsik dan ekstrinsik. Oleh karena karya seni adalah soal konsensus sosial tentang suatu benda, maka aspek intrinsik benda tersebut (seluruh aspek formal-komposisionalnya) tidak lain daripada perwujudan aspek ekstrinsiknya (seluruh sistem pembagian kerja yang mendorong terbentuknya segala aspek formal-komposisional tersebut). Begitu disadari bahwa karya seni tak lebih daripada produk konsensus sosial, maka yang-intrinsik menjadi efek dari yang-ekstrinsik. Situasi ini mendorong terwujudnya hubungan yang baru antara seni dan perubahan sosial.
Dengan bertumpu pada kesadaran baru itu, kini karya seni tidak lagi dipertentangkan dengan perubahan sosial. Tak ada lagi pertentangan antara seni sebagai instrumen atau sarana perubahan sosial dan seni sebagai wilayah aktivitas yang otonom. Karena suatu benda hanya bisa menjadi karya seni sejauh ada hubungan sosial yang menempatkannya pada posisi tersebut, dan hubungan sosial tak pernah steril dari ideologi dan kepentingan ekonomi-politik, maka otonomi seni adalah isapan jempol. Disadari atau tidak, diakui atau tidak, seni adalah bagian dari proses perubahan sosial. Di sini kriteria evaluasi atas mutu karya seni pun bergeser. Kita tak bisa lagi memakai kriteria evaluasi yang sepenuhnya formal untuk membaca karya seni, sebab begitu diakui bahwa karya seni adalah produk dari suatu proses pembentukan konsensus dalam masyarakat, maka persoalan keindahan estetik menjadi amat sekunder dan tergantung pada konsensus yang membentuk selera estetik dalam publik seni terkait. Kriteria utama yang kini lebih banyak mengedepan dalam evaluasi karya seni adalah sejauh mana karya tersebut dapat mendorong terciptanya hubungan-hubungan sosial yang baru, menciptakan kenyataan sosial baru. Karena karya seni pada hakikatnya adalah sebentuk hubungan sosial, maka kriteria evaluasi paling intrinsik terhadapnya adalah sejauh mana karya tersebut mampu menghadirkan pengalaman yang paling intens akan hubungan sosial.
Di Barat, inilah kecenderungan yang mengemuka pasca-seni konseptual di era 1960-an. Sementara di Indonesia, kecenderungan ini mulai nampak sesudah Gerakan Seni Rupa Baru era 1970-an. Banyak karya seni konseptual, semisal karya-karya Barbara Kruger, yang mendorong pemirsanya untuk memikirkan segala apa yang diketengahkan oleh karya dan karenanya mendorong pemirsa itu untuk menginterogasi kembali keyakinannya selama ini sehingga berdampak pada terbentuknya hubungan sosial yang baru. Street artist seperti Banksy bekerja dengan cara yang serupa: menghadirkan persepsi baru tentang kenyataan di tengah-tengah ruang publik sehingga persepsi ini akan mendorong timbulnya hubungan sosial baru. Demikian pula dengan ‘seni rupa komunitas’ yang dipraktikkan oleh Moelyono di Tulungagung dan Arief Yudi di kecamatan Jatiwangi, yakni mengubah kenyataan sosial di sekitar melalui praktik seni partisipatoris yang melibatkan warga. Bedanya adalah bila seni konseptual dan street art masih menempatkan pemirsa sebagai konsumen benda seni yang kemudian ditransformasi menjadi agen perubahan dalam masyarakat, seni rupa komunitas menempatkan pemirsa sejak mula sebagai pencipta ‘karya seni’, yakni kenyataan sosial yang baru. Terlepas dari perbedaan corak aktif atau pasif, partisipatoris atau non-partisipatoris, praktik-praktik kesenian baru pasca-1960-an umumnya semakin mengalami pergeseran dari yang mulanya kontemplatif menjadi transformatif.
Pergeseran Subjek Seni
Perubahan arti objek seni juga terjadi bebarengan dengan pergeseran pengertian tentang subjek seni atau ‘seniman’. Wawasan peninggalan zaman Romantik yang mengkultuskan seniman sebagai sosok pencipta yang sublim dan adiluhung sudah banyak ditinggalkan dalam praktik seni kontemporer. Pergeseran ini juga turut dimungkinkan oleh meningkatnya kesadaran tentang akar sosial dari setiap karya seni. Begitu karya seni dipandang sebagai produk pengakuan sosial dan karenanya dikondisikan oleh hubungan sosial tertentu, status seniman sebagai pencpta pun tergusur. Yang menciptakan karya seni bukanlah seniman, melainkan masyarakat atau publik seni secara bebarengan. Seniman hanya menghasilkan benda—tetapi publik kemudian membaptis benda itu jadi karya seni. Dengan begitu, tumbanglah konsepsi usang tentang seniman sebagai creator.
Dengan pergeseran itu, terjadilah suatu demokratisasi atas proses produksi artistik. Penciptaan karya seni bukan lagi hak privilese seniman, melainkan setiap anggota masyarakat. Dari sinilah timbul kesadaran bahwa setiap orang adalah seniman. Kesadaran ini mengemuka dengan mencolok antara lain dalam estetika partisipatoris Augusto Boal berkenaan dengan seni teater. Melalui analisis sejarah seni, Boal memperlihatkan bahwa sistem teater yang bertopang pada representasi ketokohan dalam sosok protagonis individual bukanlah sesuatu yang alamiah atau ada sejak mula. Sistem tersebut baru diciptakan oleh Thespis di abad ke-6 SM. Sebelumnya lakon teater tidak dipentaskan oleh aktor-aktor individual, melainkan dinarasikan dan dinyanyikan secara kolektif oleh paduan suara (chorus). Apabila kita mundur lebih jauh lagi ke awal praktik seni teater, menurut Boal, kita tak akan menjumpai perbedaan antara pemain dan pemirsa sama sekali. Sistem yang memisahkan seniman teater dari pemirsa, baik dalam sistem choral maupun protagonis, hanya dimungkinkan oleh suatu pembagian kerja artistik antara seniman dan pemirsa. Kenyataannya, bagi Boal, praktik seni teater paling awal tidak mengenal pembagian kerja semacam itu. Apa yang disebut pertunjukan teater mulanya adalah pesta rakyat di mana semua orang menyanyi, bermain peran dan minum anggur bersama. Dengan demikian, Boal menunjukkan bahwa pada hakikatnya setiap orang adalah seniman karena distingsi antara seniman dan pemirsa, antara sang ‘ahli seni’ dan ‘masyarakat awam’, bukanlah suatu keniscayaan historis.
Berdasarkan kesadaran bahwa setiap orang adalah seniman, kemudian Boal mengembangkan praktik seni yang dikenal sebagai ‘teater forum’ di mana panggung menjadi tempat diskusi antara aktor dan pemirsa tentang cara-cara yang mesti ditempuh agar menghasilkan akhir cerita yang lebih baik. Di sana, tak ada distingsi tegas antara pemain teater dan pemirsa karena setiap pemirsa dapat menginterupsi pertunjukan dan memberikan saran ataupun terlibat memerankan tokoh dalam pertunjukan. Pada era 1990-an, Boal mempraktikkan pengembangan lanjutan dari praktik artistik semacam itu ke ranah pengambilan kebijakan politik—suatu ‘teater legislatif’. Apabila teater forum mengubah pemirsa menjadi aktor, teater legislatif mengubah warga negara menjadi legislator. Ketika ia menjabat sebagai walikota Rio de Janeiro, ia menyiapkan panggung teater khusus tempat setiap warga dapat mengajukan usulan undang-undang dengan jalan mementaskan suatu pertunjukan teatrikal yang mengedepankan usulan tersebut. Ada belasan undang-undang yang berhasil disahkan Boal dari praktik teater legislatif ini, misalnya ketentuan bahwa tanggal 7 Desember akan diperingati sebagai Hari Solidaritas Rakyat Timor Leste.
Apabila setiap orang adalah seniman, lalu apa fungsi yang tersisa bagi seniman profesional? Ia berperan sebagai organizer. Jika setiap orang adalah pencipta karya seni, dan setiap karya seni tidak lain adalah hubungan sosial, maka tugas seniman profesional hanyalah menjadi penghubung yang mengkoordinasikan massa, sebagai para pencipta karya seni, sehingga menciptakan sehimpun hubungan sosial yang baru dan, dengan cara itu, kenyataan sosial yang baru. Gagasan semacam ini belakangan diteorikan dalam tajuk ‘estetika relasional’, antara lain oleh Nicolas Borriaud. Menurut paradigma estetika semacam ini, praktik kesenian sejatinya tertanam dalam ruang sosial sehari-hari dan tidak terkunci dalam ruang khusus yang masih dibayangkan oleh para penganut teori seni institusional sekalipun—ruang elit yang tercipta dari hubungan antara seniman, kurator, pemilik galeri dan kolektor. Berbeda dari ruang khusus semacam itu, ruang sosial sehari-hari berarti ranah interaksi sosial yang lazim terjadi di masyarakat, bisa ruang-ruang urban seperti venue hipster, perkampungan kumuh kaum miskin kota, atau bisa juga ruang-ruang komunitas di tingkat desa. Di ranah umum seperti itulah praktik kesenian kontemporer yang partisipatoris terjadi.
Intervensi seniman dalam mentransformasi ruang sosial dan segenap hubungan sosial di dalamnya tidak diwujudkan berdasarkan suatu aspirasi avant-garde yang berpretensi menjadi agen perubahan dan lalu menggurui massa agar mengubah relasi sosialnya. Pendekatan khas pejabat dan pemuka agama itu tak berlaku dalam estetika relasional sebab estetika ini berangkat dari asumsi bahwa semua orang adalah agen perubahan sosial sehingga kapasitas transformasi sosial bukanlah privilese seorang seniman tercerahkan yang ‘turun ke bawah’, melainkan kapasitas kolektif massa itu sendiri. Sang seniman terlibat dalam proses musyawarah bersama, memberikan saran dan ikut bekerja bersama mewujudkan agenda-agenda kolektif masyarakat setempat. Produknya bisa apa saja, mulai dari yang masih berkaitan dengan ‘benda seni’ (misalnya pameran seni di tingkat kampung) sampai dengan bentuk kegiatan yang tak ada sangkut pautnya dengan ‘benda seni’ (misalnya gerakan ekonomi mandiri yang resisten terhadap hubungan sosial-produksi kapitalis). Ada/tidaknya ‘benda seni’ tak lagi menjadi tujuan dari praktik kesenian relasional sebab praktik ini dilandasi oleh kemawasan bahwa seni pada dasarnya adalah hubungan sosial dan karenanya tak bisa direduksi pada benda. Kalaupun praktik seni nir-benda semacam itu mau dipamerkan dalam event seni konvensional (seperti biennale), maka yang dipamerkan lebih sering adalah dokumentasi dari proses kolektif itu.
Dilema Seni Partisipatoris
Dengan demikian, kita sudah saksikan bagaimana terobosan dalam produksi artistik telah berhasil menjawab dilema klasik seputar seni emansipatoris. Karya seni tak lagi bisa dipandang sebagai ‘benda seni’, tetapi lebih terutama sebagai himpunan relasi sosial yang baru. Seniman tak lagi bisa dipandang sebagai ‘pencipta’, tetapi lebih cenderung sebagai seorang organisator yang bekerja di tengah masyarakat. Kedua jenis pergeseran ini, pada aras objek maupun subjek seni, memperlihatkan bagaimana dilema klasik antara bentuk dan isi, antara keindahan dan kegunaan, serta antara otonomi dan keberpihakan, diselesaikan dalam praktik. Dalam praktik produksi artistik semacam ini, bentuk merupakan konsekuensi logis dari isi. Bentuk artistik dipilih sejauh ada keperluan untuk menyatakan sesuatu dalam konteks sosio-historis yang spesifik. Pilihan mengapa kolektif seni di Jatiwangi memilih wahana tanah liat sebagai wahana utama proses artistiknya dijawab oleh latar sosio-historis khas Jatisura sebagai desa produsen genting dari tanah liat secara turun-temurun. Pilihan mengapa produk seni yang diwujudkan dari wahana tanah liat itu adalah alat musik juga dijawab oleh latar kebutuhan para pemuda desa yang gemar main musik. Jadi bentuk artistik tidak direka-reka berdasarkan inspirasi sublim sang seniman soliter, melainkan diwujudkan sebagai jawaban atas kebutuhan sosio-historis masyarakat setempat. Inilah tiga tonggak seni partisipatoris: seniman sebagai organizer, karya seni sebagai hubungan sosial dan pilihan bentuk artistik sebagai perwujudan dari kebutuhan sosio-historis masyarakat.
Namun dilema seni emansipatoris juga masih menghantui seni partisipatoris. Dikotomi antara bentuk dan isi rentan timbul kembali dalam rupa dikotomi antara aspek ‘seni’ dan aspek ‘partisipasi’ dari praktik seni partisipatoris. Tegangan ini bersumber dari dua arus yang secara tradisional berlawanan, yakni arus ‘seni murni’ dan arus ‘aktivisme sosial’. Masing-masing eksponen dari kedua arus tersebut sering mengajukan dua pertanyaan berikut:
- ‘Mana seninya?’
- ‘Mana partisipatorisnya?’
Dua pertanyaan inilah yang lazim diutarakan berkenaan dengan praktik seni partisipatoris kontemporer. Pertanyaan pertama lazim diajukan oleh para penghayat ‘seni murni’, sementara pertanyaan keduanya biasanya dilontarkan oleh para aktivis sosial.
Dari perspektif penghayat ‘seni murni’, apa yang dilakukan Moelyono dan Arief Yudi bukanlah praktik kesenian, melainkan praktik advokasi sosial yang lazim dijalankan oleh para aktivis LSM. Seni, dalam pandangan tradisional ini, selalu berhubungan dengan produksi benda seni dengan seluruh elemen formal-komposisionalnya yang dapat dievaluasi secara estetis. Namun pendapat semacam ini mudah disanggah-balik. Pendapat itu masih bertopang pada asumsi bahwa karya seni identik dengan benda seni dan bahwa seniman adalah seorang creator benda seni. Dan asumsi semacam itu sudah kadaluarsa akibat pergeseran praktik kesenian sesudah era 1960-an. Anggapan semacam itu lazimnya muncul dari para pegiat seni yang mengandalkan galeri komersial dan penjualan karya secara konvensional. Secara ekonomi-politik, pandangan semacam itu bisa bertahan karena semaraknya pasar seni rupa yang dengan sendirinya memprioritaskan benda seni—sebab hanya ‘benda seni’ lah yang bisa dikomodifikasi dengan cepat, bukan hubungan sosial.
Namun bukan berarti hubungan sosial kebal terhadap proses integrasi ke dalam rantai kapitalisme. Justru landasan konsolidasi kapital, yakni hubungan kerja-upahan, merupakan bentuk hubungan sosial paling awal yang diserap ke dalam tatanan kapitalis. Dalam konteks seni partisipatoris, masalahnya cuma waktu. Pasar butuh waktu untuk membiasakan diri dengan produk seni non-bendawi seperti hubungan sosial. Jika suatu saat nanti hubungan-hubungan sosial yang tercipta dari praktik seni partisipatoris dapat dikapitalisasi seperti halnya pasar seni rupa mainstream saat ini, barangkali saat itulah seni rupa partisipatoris baru akan diterima dalam kanon ‘seni murni’ dan diakui oleh para pemilik galeri komersial dan kolektor. Jadi, sebelum saat itu tiba, para seniman partisipatoris mesti memutar otak untuk menyiasati jebakan batman para tengkulak seni. Mereka mesti mencari celah untuk mengubah hubungan sosial-produksi kapitalis sehingga terhindar dari gempuran kapitalisme. Dengan kata lain, para seniman partisipatoris pada akhirnya akan semakin didorong untuk kritis terhadap kapitalisme bila mereka hendak bertahan sebagai seniman partisipatoris dan bukan cem-ceman kolektor. Radikalisasi praktik seni partisipatoris cuma soal waktu.
Dari perspektif aktivis sosial dan politisi progresif yang tak sabaran, apa yang dilakukan para seniman partisipatoris kerap juga dipertanyakan: ‘Di mana dimensi partisipatorisnya?’ Terlepas dari asumsi soal kesetaraan estetis yang diandaikan dalam praktik-praktik seni partisipatoris dewasa ini, masih perlu diperiksa lagi bagaimana hal itu terwujud secara konkrit. Apabila kita menyelenggarakan suatu pekan kesenian di kampung dan mengundang para seniman kontemporer untuk memamerkan karyanya di sana, lantas sungguhkah ada peran partisipatoris warga setempat selain sebagai penonton yang duduk termangu memandangi citra visual yang demikian asing di matanya? Kalau cuma berpartisipasi sebagai penonton, rumput juga berpartisipasi. Kalau kita menyelenggarakan suatu pentas musik dengan membawakan lagu-lagu M83 atau St. Vincent di sebuah desa yang hanya mengenal lagu dangdut dan pop Nusantara, lantas sungguhkah ada peran partisipatoris warga setempat selain sebagai partisipan ‘gegar budaya’? Kalau cuma bikin gegar budaya, FPI juga bikin gegar budaya. Kalau cuma bikin situasi awkward, Kodim juga bisa bikin situasi awkward. Contoh-contoh ekstrem ini hanya untuk menunjukkan bahwa tidak semua yang ‘turun ke bawah’ itu otomatis partisipatoris—masih harus diperiksa lagi strategi partisipasi yang ditawarkan.
Di balik praktik seni berbasis komunitas selalu ada risiko ‘gentrifikasi estetis’ atau ‘pengkelas-menengahan selera estetis’ seperti yang dicontohkan tadi. Risiko ini dengan sendirinya mengarah pada kecenderungan avant-gardisme yang sebetulnya mau ditampik oleh praktik seni partisipatoris. Seni avant-garde selalu punya pretensi menggurui, menjadi yang terdepan dan mencerahkan mereka yang secara kultural tertinggal di belakang. Karena itu, kalaupun seniman avant-garde punya kecenderungan untuk ‘turun ke bawah’, artikulasinya kerap kali mewujud dalam patronase kultural baru. Dalam hal ini, seniman partisipatoris mesti belajar lagi dari sejarah gerakan Proletkult di Rusia era 1920-an. Dengan seluruh pretensi avant-garde-nya, para seniman suprematis dan Modernis di Rusia turun ke desa dengan membawa lukisan-lukisan yang sepenuhnya asing bagi warga desa yang hanya mengenal ragam hias tradisional. Para seniman ini menampilkan karya-karya seni modern itu sebagai buah kebudayaan Rusia baru yang maju secara intelektual. Dengan itu, mereka berpretensi menciptakan kebudayaan komunis yang baru, yang terbebaskan dari segala pengaruh tradisi kolot dan paham tua. Gerakan Proletkult ini dikritik keras oleh Lenin yang beranggapan bahwa kebudayaan baru tak bisa dihasilkan dari inspirasi sublim segelintir seniman garda-depan, melainkan hanya bisa dirakit dan disuling dari praktik-praktik kultural masyarakat yang ada. Kritik Lenin ini masih relevan untuk menangkal risiko ‘gentrifikasi estetis’ atau ‘avant-gardisme anti-mainstream’ dalam praktik seni partisipatoris kontemporer.