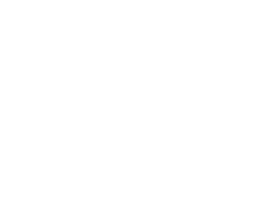Pada malam pertama bulan Mei, Sikka Convention Center tampak penuh dilihat dari pintu masuk. Di dalamnya sedang berlangsung festival teater pelajar Maumerelogia yang merupakan bagian dari Temu Seni Flores. Lalu lintas dari pintu masuk agak macet karena beberapa pengunjung berhenti untuk melihat lapak buku yang terletak persis setelah pintu masuk.
“Berapa harga bukunya?” tanya saya kepada salah satu penjual, yang ternyata, adalah anggota komunitas KAHE (Sastra Nian Tanah). Komunitas itu sendiri adalah komunitas sastra di Maumere.
“Ini Rp 30 ribu, yang itu Rp 50 ribu,” ujarnya.
Membuka lapak buku di acara-acara seni adalah salah satu cara penulis di NTT dalam menjual karya mereka. Pada acara di atas, misalnya, tampak buku-buku yang tidak hanya berasal dari Maumere, di mana kebanyakan diproduksi Komunitas Kahe, namun juga dari kota lain seperti Kupang dan Larantuka.
Produksi dan distribusi buku harus diusahakan sendiri oleh penulis-penulis di NTT. Pada tahapan produksi saja, penulis di sini mencetak buku dengan biaya sendiri. Itu pun beberapa dilakukan di luar NTT.
“Buku saya yang berjudul Hawa dicetak di Jogja,” tutur Sandra Olivia Frans. “Prosesnya memakan waktu kira-kira sebulan.”
Sementara sebagian yang lain mencetak di dalam NTT, seperti buku Tuhan Mati di Biara karya Hans Hayon. Penerbitnya sendiri adalah Nusa Indah, sebuah penerbit di Ende yang sudah lama berdiri. Komunitas Dusun Flobamora di Kupang dengan jurnal andalan mereka, Santarang, juga dicetak langsung di Kupang.
Sumba, Maumere, dan Kupang merupakan kota-kota yang mengalami pertumbuhan sastra, namun hanya ada satu toko buku berskala nasional di NTT yang terletak di Kupang. Sandra yang tinggal di Soe harus menempuh jarak 110 km jika ingin membeli buku. Di Soe sendiri hanya ada satu perpustakaan daerah.
Saat ditanya mengapa tidak menjual buku di toko buku tersebut, Sandra menjawab singkat. “Mahal.”
“Namun ada temanku yang bukunya dijual di sana,” jawab Linda Tagie yang berdomisili di Kupang. “Bukunya Hans Hayon itu.”
Martha Hebi mengungkapkan apa yang menjadi kelebihan para penulis NTT. “Untungnya inisiatif teman-teman tinggi. Selalu ada kesadaran untuk mendokumentasikan karya. Mereka mengumpulkan karya-karya yang sudah ada, baik yang sudah dibagi di sosial media atau koleksi pribadi menjadi sebuah buku.”
Cerita Martha Hebi ini mengingatkan saya di sebuah diskusi Perempuan dan Sastra – Temu Seni Flores, tentang terbitan para penulis NTT yang jenis umumnya adalah antologi. [1] “Di Sumba, belum ada komunitas yang menerbitkan buku. Yang ada adalah anggota komunitas itu menerbitkan buku secara individu. Misalnya Stefanus Segu dan Diana D Timoria. Dukungan komunitas ada di bagian merancang konsep peluncuran buku dan mencarikan pembicara.”
Martha membantu temannya dengan ikut mempromosikan buku di media sosial. “Di Waingapu, hanya ada satu toko buku gereja bernama Waingapu. Saya biasanya mengambil buku langsung 10 buah agar teman saya dapat membelinya lewat saya. Radio lokal juga dijadiin tempat titip jual.”
“Kalau ada teman yang sedang di Jawa, kita juga nitip,” ujar Linda. “Makanya waktu saya ke Jakarta, saya ke Blok M Square memborong buku. Itu semua titipan teman.”
Pesan lewat pos juga dilakukan meski konsekuensinya adalah tarif pengiriman yang lumayan. “Jika ada pesanan dari Maumere, mereka beli sebanyak-banyaknya agar satu paket. Ongkos kirim Kupang-Maumere sudah Rp 20.0000-an. Ongkos kirim Jakarta-Kupang malah bisa Rp 40.000. Makanya kita suka bertukar pinjam buku. “
Regenerasi Sastra NTT
Sastra NTT punya sejarah panjang. Menurut Yohanes Sehandi selaku pengamat sastra senior di NTT, tonggak sastra NTT dapat ditesuri sejak 1961. Tahun itu menjadi momentum penting karena ada data otentik tentang seorang penulis NTT yang mempublikasikan karya sastranya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ia adalah Gerson Poyk, sastrawan NTT yang meninggal pada Februari silam. Cerpennya berjudul Mutiara di Tengah Sawah dimuat dalam majalah Sastra (edisi Tahun I, Nomor 6, Oktober 1961) dan mendapat hadiah sebagai cerpen terbaik tahun itu.[2]
Seni sastra di NTT sudah memasuki generasi keempat. Mereka adalah penulis yang lahir medio 1991-2001, seperti Mario F Lawi dari Kupang dan Erwyn Lasar dari Maumere. Generasi pertama (1931-1950) antara lain ditandai oleh Gerson Poyk dan Ignas Kleden; berikutnya generasi kedua (1951-1970) ada Mezra Pellondou dan Marsel Robot; sedangkan generasi ketiga (1971-1990) diwakili Amanche Franck Oe Ninu dan Christian Dicky Senda.[3]
Dalam lima tahun terakhir memang terjadi perkembangan pesat. Misalnya, diselenggarakannya Temu Sastrawan NTT (2013 dan 2015) oleh Kantor Bahasa Prov. NTT dan Festival Sastra Santarang (2014) oleh Komunitas Dusun Flobamora dan Komunitas Salihara. Kantor Bahasa sendiri punya acara rutin, seperti Kelas Literasi untuk guru-guru SD, SMP, dan SMA serta Bengkel Sastra.
“Acara tersebut menjadi ajang pertemuan para penulis NTT karena sebelumnya kami hanya bercakap lewat media sosial. Tamu yang diundang juga dari luar, seperti AS Laksana, Ayu Utami, dan Hasif Amini,” kata Linda. Acara berskala kecil inisiatif komunitas juga dapat ditemukan di Ende dan Kupang, seperti Malam Puisi Ende (Komunitas SARE dan Puisi Jelata) dan BABASA – Bincang dan Babasa Sastra (ALPHI Music Studio, Rumah Poetica, dan Dusun Flobamora).
Yohanes Sehandi melakukan pemetaan jumlah produksi sastra. Tulisnya, pada 2011 terdapat 15 buku yang terbit. Buku-buku tersebut terdiri dari enam novel, tiga antologi cerpen, dan enam antologi puisi.[4] Dalam catatannya, sejak kurun 1961-2015 sastrawan NTT berjumlah 44 orang dengan produksi 135 buku. Ia bilang jumlah ini ‘bukan apa-apa’ karena karya sastra dari NTT sulit ditemukan di pasaran karena tidak dicetak ulang penerbitnya maupun pengarangnya.[5]
Perbaikan manajemen produksi buku disertai komitmen setidaknya terlihat di Jurnal Santarang yang diterbitkan Komunitas Dusun Flobamora. Santarang yang berisi cerpen, esai, kritik sastra, karikatur, dan humor ini sudah mencapai edisi 58. Adapun kontributor berasal dari luar NTT, seperti Joko Pinurbo dan AS Laksana. Santarang lantas menjadi tolak ukur penulis di NTT karena menjadi satu-satunya jurnal yang dikurasi.
“Kita jual lewat media sosial dan selalu habis. Biasanya kita cetak 150-300 eksemplar. Santarang selalu habis terjual karena punya pelanggan tetap, seperti guru bahasa, pastor, mahasiswa, dsb”, ujar Linda. Sejak Februari 2017 Santarang hanya terbit secara daring karena kebijakan redaksi yang ingin mengubahnya menjadi format majalah. Rencananya majalah ini akan terbit triwulan dengan jumlah 100 halaman.
Media lokal seperti Pos Kupang, Timor Express, Victory News, dan Flores Pos dianggap cukup berperan sebagai wadah publikasi dan mendorong pertumbuhan penulis. Siapa saja bisa mengirimkan karya dan dimuat dengan mudah.
“Tapi masih ada yang kurang dari editorial terbitan-terbitan kita”, tutur Sandra. “Sebagian besar editannya terbatas pada pengecekan ejaan saja.”
Pada 2017 ini berarti usia jejak sastra NTT adalah 56 tahun. Editor dan promosi menjadi sosok yang dibutuhkan.
* Judul disadur dari judul novel “Cumbuan Sabana” karya Gerson Poyk (1979).
[1] “Temu Seni Flores: Menggali Narasi-Narasi di Ende dan Maumere” http://koalisiseni.or.id/temu-seni-flores-menggali-narasi-narasi-ende-dan-maumere/
[2] “Sejarah Awal Sastra NTT” http://uniflor.ac.id/berita/detail/Sejarah-Awal-Sastra-NTT
[3] “Orang NTT di Panggung Sastra” http://kupang.tribunnews.com/2016/07/22/orang-ntt-di-panggung-sastra
[4] “Selamat Datang Kritikus Sastra NTT” http://media-ponorogo.blogspot.co.id/2015/12/selamat-datang-kritikus-sastra-ntt.html
[5] “Sejarah Awal Sastra NTT” http://uniflor.ac.id/berita/detail/Sejarah-Awal-Sastra-NTT