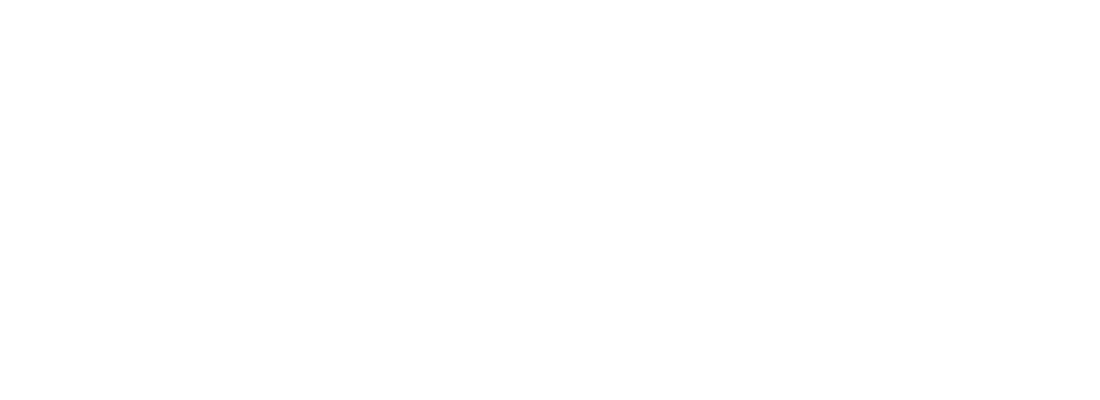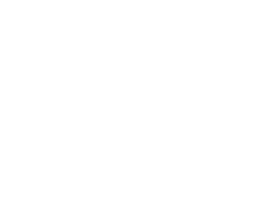Genting adalah Jatiwangi, dan Jatiwangi adalah genting.
Sudah puluhan tahun warga kecamatan di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, tersebut menggantungkan hidupnya pada ratusan pabrik genting, yang dikenal sebagai jebor dalam istilah setempat. Krisis moneter 1998 membuat industri genting merosot, perekonomian lokal melemah, dan masyarakat kehilangan kegembiraannya.
“Masalahnya, dulu mereka baru bergembira saat dapat uang dari menjual genting. Kami ingin mengajak masyarakat bergembira dan bangga bukan hanya dari hasil penjualan. Tapi dari identitas mereka sebagai orang yang berkarya dan melindungi jutaan manusia yang bernaung di bawah gentingnya,” ujar Arief Yudi Rahman, seniman yang lahir dan tumbuh di Jatiwangi.
Pada 2005, ia menggagas Jatiwangi art Factory (JaF) bersama istrinya, Loranita Theo, adiknya, Ginggi Syarief Hasyim, serta Deden Imanudin dan Ketut Aminudin. Mereka sepakat menggunakan seni untuk mengembalikan kegembiraan warga Jatiwangi. “Seni menangkap dan menajamkan apa yang ada dalam keseharian. Ia menyumbang tafsir dan rasa pada apa yang dilakukan setiap hari. Maka kita bisa gembira dan berumur panjang karena tidak terpaku pada rutinitas,” ucap Arief.
Para inisiator menjadikan JaF sebagai organisasi sosial berupa ruang kreatif seni budaya yang memberdayakan kehidupan pedesaan dan menyelesaikan konflik masyarakat. Bekas pabrik genting milik keluarga Arief direnovasi menjadi ruang seni berjudul Jebor Hall sebagai pusat kegiatan JaF.
Festival Sebagai Fondasi
Kegiatan JaF sangat beragam, namun awal dan tulang punggungnya adalah serangkaian festival yang melibatkan seniman dan warga. Dalam tiga festival berbeda, seniman nusantara dan mancanegara bermukim di salah satu rumah warga di 16 desa di Jatiwangi, berinteraksi dengan penduduk, berkolaborasi dalam karya seni, lalu menampilkannya bersama-sama. Konsep tamu-tuan rumah ini bermaksud menembus batas-batas praktik seni dan mendorong penciptaan karya yang merefleksikan ide, tradisi, dan isu dari komunitas lokal, dipadukan dengan ide dan praktik artistik seniman mukiman.
Festival Residensi Jatiwangi dilaksanakan setiap tahun dengan fokus pada seni kontemporer. Awalnya bernama Jatiwangi International Performing Arts-in-Residence Festival, perhelatan ini pertama kali diadakan pada 2006. “Seniman luar tertarik karena mereka lihat ada seni kontemporer bisa masuk ke warga biasa tanpa pengetahuan seni. Ini berbeda dengan menampilkan karya di galeri seni, yang hadirinnya memiliki pengetahuan seni dan bisa membaca karya mereka,” tutur Arief.
Bekerja sama dengan Sunday Screen, kelompok pembuat video dari Bandung, JaF menyelenggarakan Festival Video Desa tiap dua tahun. Residensi dilakukan selama dua pekan, saat pembuat video berkolaborasi dengan penduduk dan aparat desa. Dalam prosesnya, penduduk dilatih memetakan masalah dan kejadian sehari-hari. Video yang mendokumentasikan kehidupan desa lantas diputar dalam acara pada akhir festival.
Ada pula Festival Musik Keramik yang diadakan setiap tiga tahun. Seperti namanya, perhelatan ini berfokus pada musik yang terbuat dari keramik, olahan tanah liat. Acara ini menggali dan menggunakan lagi beragam alat musik keramik tradisional yang sempat hilang dari masyarakat. “Waktu saya kecil, banyak orang memainkan suling tanah. Ini kemudian hilang, tapi digali kembali dan kami malah belajar dari Youtube,” kata Arief. “Kami juga belajar dari internet, bagaimana cara menggunakan genting sebagai perkusi dan memaksimalkan bunyinya, jadi seperti gamelan.”
Pada penyelenggaraan pertamanya tahun 2012, festival dibuka dengan lebih dari 1.500 orang menabuh genting yang menghasilkan irama rancak. Pada 2015, jumlah penabuh genting melonjak menjadi lebih dari 5.000 orang. Dalam festival ketiga yang akan diadakan November 2018, diperkirakan jumlahnya akan bertambah lebih banyak lagi.
Dari Forum hingga Museum
Di sela-sela festival, JaF melaksanakan beragam kegiatan. Forum 27an, misalnya, adalah serial diskusi bulanan yang diadakan setiap tanggal 27. Selain penanda tanggal, nama acara ini mengandung arti lain, yakni forum untuk mencapai dua tujuan. Pertama, menyelesaikan masalah, dan kedua, menyasar ke dalam diri sebagai sebentuk introspeksi. Dalam forum, semua warga Jatiwangi bisa datang untuk mengobrolkan pikiran, ide, dan pendekatan dalam berbagai bidang. Tak cuma seni yang dibahas, masalah ekonomi, pendidikan, dan politik juga sering muncul.
Untuk anak muda, ada Apamart, ajang berupa pasar bulanan. Acara ini dimaksudkan agar anak muda mengembangkan pengetahuan dagang dan menyebarkan jaringan pertemanan secara langsung. Uniknya, alat pembayaran Apamart berupa uang koin dari tanah. Selain gerai pedagang, Apamart juga diisi pentas musik dan lokakarya untuk remaja. Beda lagi untuk anak-anak. JaF rutin mengunjungi sekolah-sekolah di Jatiwangi untuk menggelar lokakarya pembuatan keramik. Anak-anak kelas 3 hingga 6 SD menjadi pesertanya.
Dalam bidang audiovisual, ada televisi komunitas bertajuk JaF TV, yang menayangkan informasi relevan untuk warga Jatiwangi. Acara disiarkan selama sekitar enam jam tiap hari, terdiri atas program berita, hiburan, pendidikan, dan acara anak-anak. Ada pula JaF Radio, yang jangkauan pancaran sinyalnya mencapai radius 50 km. Dengan pengantar bahasa Sunda, bahasa ibu penduduk Jatiwangi, radio ini mengeksplorasi isu-isu lokal dan kerap mengadakan acara off-air untuk menjalin hubungan dengan pendengarnya.
Adapun Bakar Berjamaah ialah perhelatan khusus sebelum Festival Musik Keramik. Dalam acara ini, ribuan suling tanah, yang dibuat bersama-sama oleh para warga, dibakar agar bisa digunakan saat festival berlangsung. Menyertai pembakaran, diadakan juga pengajian sebagai wujud syukur sekaligus doa demi kelancaran acara.
Pada September 2018, JaF meresmikan Museum Kebudayaan Tanah untuk melestarikan aset kebudayaan yang berkaitan dengan tanah. “Museum ini tidak hanya untuk menyimpan kenang-kenangan masa lalu, tapi juga untuk membuat kenang-kenangan masa depan. Tidak hanya karya JaF yang bisa disimpan di museum ini, tapi juga karya tentang kebudayaan tanah lainnya,” tutur Ginggi.
Saat Masyarakat Terlibat
JaF berdiri dengan gagasan untuk membuat warga desa mengalami kenikmatan berkesenian—yang melekat alamiah dengan kenikmatan berpikir, berpendapat, mengenal, dan menganalisis diri. Warga adalah unsur mutlak dalam seluruh rangkaian kegiatan JaF. Awalnya, tim JaF berinisiatif mengundang seniman luar untuk bermukim di desa. Untuk melibatkan warga, JaF mengadakan pertemuan di semua desa di Jatiwangi dan berunding. Warga ditawari, apakah bersedia menyediakan sepiring ekstra nasi dan lauk pauk untuk para seniman yang bermukim; atau meminjamkan rumahnya menjadi tempat pameran karya.
“Awalnya, warga ada yang mengerti dan percaya, ada juga yang curiga. Kami percaya dengan konsistensi, jadi terus melakukan kegiatan meski responsnya berbeda-beda,” ucap Ginggi. Perlahan warga sadar bahwa Jatiwangi bisa dikunjungi dan menjadi menarik untuk orang luar. Neng, salah satu penduduk Jatiwangi, mengaku senang rumahnya menjadi ruang pamer karya seni. “Kalau ada yang datang, suami saya akan berusaha menjelaskan makna lukisan yang dipamerkan, menurut pemahamannya,” ucap Neng.
Sistem ruang pamer ini serupa galeri seni profesional. “Kalau terjual, warga pemilik rumah akan mendapat 15 persen. Karya ditaruh di rumah mereka sesuai waktu pelaksanaan pameran, kadang dua minggu, kadang sebulan. Kami sesuaikan karakteristik seniman dan tuan rumah, tidak asal meletakkan karya,” kata Ginggi.
Makin lama, antusiasme warga maupun seniman untuk terlibat makin tinggi. Mulai dari anak-anak, guru, pekerja pabrik genting, hingga aparat polisi dan militer ikut serta. Mereka menjadi panitia, kolaborator, dan penampil dari beragam rangkaian acara yang digadang JaF. “Sampai saya nggak kebagian tempat, semua sudah dikerjakan banyak orang. Saya mulai bingung mau apa lagi,” kata Arief sembari tertawa.
Dari segi dana, nyaris semua aspek JaF dibiayai secara swadaya, baik oleh warga maupun seniman. Sebagian kecil didapat dari pemerintah, misalnya renovasi Jebor Hall, dengan dana dari Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), dan program Belajar Bersama Maestro, dengan dukungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Kesuksesan JaF mendatangkan kegembiraan bagi warganya dan menarik perhatian banyak orang, baik seniman, media massa, maupun warga kecamatan lain. Menurut Arief, beberapa kecamatan di sekeliling Jatiwangi ingin belajar bagaimana cara menghadirkan hal serupa. Namun, katanya, mereka tidak sabar.
“Rata-rata mereka ingin kita bikin panggung, dan [membuat] orang datang, bukan program berdasarkan masalah daerah masing-masing. Padahal program [JaF] tujuannya berkumpul, menyelesaikan konflik, memiliki kesepakatan dengan visi daerahnya. Bukan hanya ingin orang luar datang berwisata. Kemewahan daerah harus lebih dulu dinikmati oleh warga lokal,” tutur Arief.
Terakota Sebagai Identitas

Sejak JaF berdiri, Jatiwangi telah banyak berubah. Pembangunan bandara internasional Kertajati dan banyak pabrik mengubah kecamatan tersebut. Makin banyak pabrik genting tutup, tanahnya dijual ke pabrik, sedangkan pekerjanya pindah ke pabrik garmen atau manufaktur lain di sekitarnya.
Arief menilai perubahan tersebut sesungguhnya menghambat mobilitas sosial-ekonomi warga. Dulu saat bekerja di pabrik genting, mereka bisa belajar segala aspek produksi genting kemudian membuka pabrik sendiri. Jika bekerja di pabrik garmen, misalnya, mereka hanya bisa terampil dalam satu hal, misal memotong pola atau menjahit. Modal peralatan juga sangat mahal. Bisa dibilang tak mungkin mereka bisa membuka pabrik garmen sendiri.
Bagaimanapun, perubahan adalah keniscayaan. Meski belum ada dampak sosial buruk yang kentara dari perubahan di Jatiwangi, JaF berupaya memitigasi dengan mencoba jalur kolaborasi. “Kami mulai bekerja sama dengan banyak pabrik, melibatkan mereka agar pemilik pabrik tahu apa yang kami lakukan. Lalu, bersama-sama berusaha mengatasi masalah sosial dari perubahan ini,” ucap Arief.
JaF berniat menjadikan Jatiwangi sebagai Kota Terakota. Ini upaya mempertahankan tanah liat agar tetap relevan dalam keseharian warga. Caranya, misalnya, dengan merevitalisasi sejumlah jebor, dan menata kecamatan itu sedemikian rupa agar dipenuhi olahan tanah liat, baik dalam bentuk genting, ubin, atau dekorasi lainnya. Monumen terakota pun rencananya dipasang di titik nol Jatiwangi.
“Beberapa teman saya sudah menawarkan untuk membantu merancang tata kotanya. Lucu juga, banyak sekali orang ingin terlibat padahal ini nggak ada uangnya,” kata Arief berseloroh. Ia juga mengungkapkan, dukungan yang paling dibutuhkan JaF adalah peningkatan kapasitas organisasi. Khususnya, bagaimana fokus pada satu titik atau misi menjadi napas semua kegiatan JaF.
Selama 15 tahun berdiri, JaF terus-menerus berkegiatan sehingga belum sempat membuat evaluasi menyeluruh terhadap organisasi dan cara kerjanya. Jika evaluasi itu bisa dilakukan, maka JaF akan lebih memahami kebutuhannya dan bagaimana cara memenuhinya. Dengan begitu, JaF bisa terus membantu warga memenuhi ikrar untuk menghormati karya leluhur dan berinovasi demi mewariskannya pada generasi mendatang—membuat kohesi sosial Jatiwangi makin erat.
Lirik lagu Baraya yang diciptakan warga dengan iringan musik tanah liat ini seolah mewakili visi JaF: “Jatiwangi tanah nu urang / Geura jaga budaya bangsa / Nu endah tur matak betah / Warisan keur anak urang.” (Jatiwangi, tanah kita. Mari menjaga budaya bangsa yang indah, yang membuat kita betah. Sebagai warisan untuk anak kita.)
*Artikel “Hidup Bergembira dari Tanah Liat” merupakan bagian dari buku Dampak Seni di Masyarakat terbitan Koalisi Seni Indonesia. Buku bisa dibeli dengan mengirimkan surel ke sekretariat@koalisiseni.or.id.