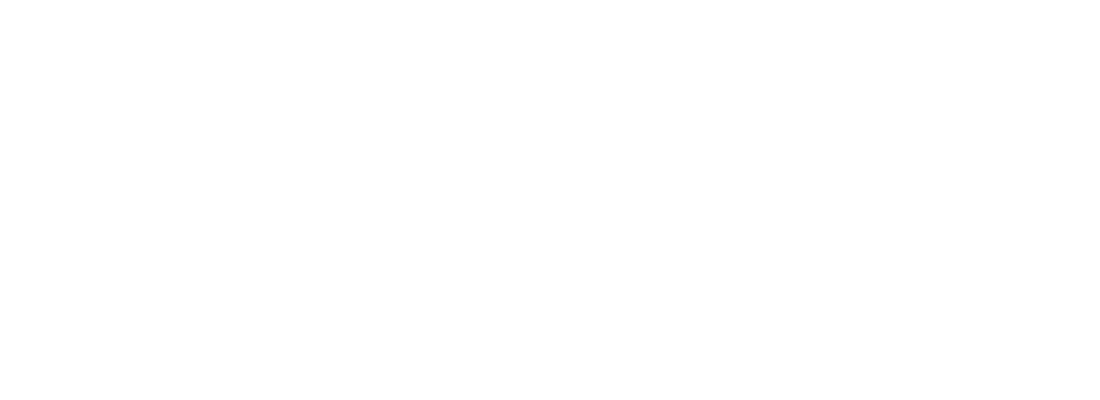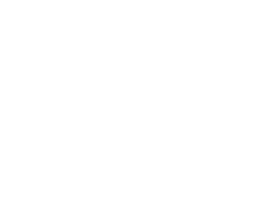Siapa yang bisa menyangka? Dari pelosok Jember bocah-bocah melanglang buana, tampil dengan tarian yang mereka karang sendiri menggunakan egrang.
Pada 2009, Farha Ciciek dan suaminya, Supohardjo, pindah dari Jakarta ke Desa Ledokombo, Jember, Jawa Timur. Mereka pulang ke kampung halaman untuk merawat ibu sang suami, yang beranjak lanjut usia. Dua anak lelaki ikut diboyong untuk tinggal di sana. Anak-anak ini sebelumnya tumbuh di Jakarta, telanjur mengenal fasilitas perkotaan. Bukan hal mudah untuk membuat mereka beradaptasi dengan kehidupan pedesaan, 35 kilometer dari pusat kota Jember.
Ingin membuat anak-anak kerasan, Supohardjo mencari-cari kegiatan yang cocok untuk membuat mereka tetap aktif. Mulailah ia mengeksplorasi hal-hal yang bisa dimanfaatkan dari lingkungan sekitar. Egrang terpilih karena bahannya mudah dan murah didapat. Lagi pula, rumahnya punya halaman luas yang bisa dimanfaatkan untuk bermain.
Kedua anak Supohardjo langsung terpikat dengan egrang, permainan yang tak mereka temukan di Jakarta dulu. Lambat laun bukan hanya mereka berdua yang bermain di halaman rumah. Anak-anak lain di sekitar rumah mulai berdatangan untuk ikut bermain. Tak hanya itu, mereka mengembangkan permainan egrang menjadi sebuah tarian. “Tarian egrang ini bukan kami yang mengembangkan, tapi anak-anak. Ketika kita memberi ruang untuk anak-anak, maka akan tercipta kreativitas,” jelas Supohardjo.
Farha dan Supohardjo kemudian tergerak untuk mendirikan Tanoker. Dalam bahasa Madura, tanoker berarti ‘kepompong’, kata yang jamak untuk mengumpamakan fase transformasi menuju masa dewasa. Komunitas Tanoker memusatkan perhatian pada proses tumbuh-kembang anak-anak, membentuk lingkungan yang gembira bagi mereka untuk bermain dan belajar. Egrang pun menjadi ikon, dan permainannya mengundang ketertarikan banyak orang untuk menonton.
Pada 2010, Farha dan Supohardjo menggagas perhelatan Festival Egrang yang pertama. Ketika masyarakat sekitar menghendaki festival diadakan kembali, Tanoker mencanangkannya menjadi festival tahunan. Perhelatannya dilakukan pada akhir pekan yang dekat dengan Hari Perdamaian Dunia, 21 September.
Sejak itu, festival ini telah memikat perhatian puluhan ribu orang. Bahkan setelah sembilan kali diadakan, Festival Egrang bukan lagi perayaan milik warga desa semata. Bupati Jember, beserta Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB), telah mengakui bahwa kegiatan ini mendongkrak nilai daerah. Anak-anak Tanoker kini telah berulang kali diundang berpentas di luar negeri, antara lain di Australia, Thailand, Jepang, China, dan Bangladesh.
Anak Sebagai Subjek

Pepatah “butuh sekampung untuk membesarkan seorang anak” mungkin ada benarnya. Menghabiskan waktu bersama anak-anak di Ledokombo menyadarkan Farha Ciciek akan hal itu. “Ternyata, parenting bukanlah persoalan pribadi, tapi persoalan masyarakat,” ungkapnya.
Di balik keceriaan anak-anak Ledokombo bermain egrang, ada beragam masalah sosial yang terjadi. Menjadi buruh migran adalah jalan yang diambil sebagian besar penduduk Ledokombo untuk lepas dari kemiskinan dan impitan utang. Tak cuma para perempuan, warga laki-laki Ledokombo juga menjadi buruh migran.
Jalan ini bukan tanpa konsekuensi. Anak-anak menjadi korbannya. Sebagian besar dari mereka tak lagi tumbuh dalam pendampingan orangtua. Banyak yang putus sekolah, menjadi pengangguran, bahkan kecanduan narkoba. Setelah orangtua pulang pun, masih ada dampak sosial lain, misalnya kekerasan terhadap anak. “Keluarga inti anak-anak ini sudah tidak utuh. Mereka jadi tidak semangat bersekolah. Kami ingin membangun (atmosfer) kalau hal tersebut harus diterima dan mereka harus tetap semangat belajar,” jelas Supohardjo.
Hati Farha dan Supohardjo terpanggil untuk melakukan sesuatu. Mereka tersadar bahwa masyarakat kerap lupa bahwa anak bukanlah objek. Anak adalah subjek. Anak juga manusia, yang berhak atas kasih sayang dalam perkembangan dirinya. Absennya keluarga yang bisa dijadikan sandaran jiwa membuat anak rentan akan reaksi negatif atas persoalan yang ia alami sehari-hari.
Sehari-harinya Tanoker mengadakan kegiatan musik dan seni untuk anak-anak. Motonya adalah “Bermain, mencerdaskan. Belajar, menyenangkan.” Setiap bulan diadakan Pasar Lumpur. Seperti namanya, berbagai kegiatan dalam Pasar Lumpur menghendaki pesertanya berani berlumuran lumpur dan kotoran. Ada outbond, permainan polo lumpur, karapan sapi, tarung bantal, estafet egrang, lomba bakiak, dan sebagainya. Seperti kata iklan di tivi, kalau tak kotor, maka tak belajar.
Mulai 2016, anak-anak yang berkegiatan di Tanoker didorong untuk ikut musyawarah desa. Lewat forum itu, mereka mengangkat perbincangan tentang hubungan orangtua dan anak, juga menyuarakan kebutuhan mereka sendiri, yakni bermain. Kebisaan menyuarakan aspirasi tak lepas dari hasil program-program pendampingan di Tanoker. Anak-anak usia 10 sampai 15 tahun dilatih untuk berorganisasi, menciptakan aspirasi, dan tentu menyuarakannya. “Dulu, kalau bicara, kepala mereka menunduk. Sekarang dagu mereka sudah sejajar untuk berkontak mata,” Supohardjo menggambarkan perubahan yang terjadi pada anak-anak yang aktif di Tanoker.
Menularkan Semangat Maju
Setiap kali membuat program, manajemen Tanoker selalu melibatkan staf kerja dari kelima divisinya. Kelima divisi itu adalah event organizer, kriya Tanocraft, unit kolam renang, penanggung jawab isu sosial dan politik, serta administrasi dan keuangan. Sebagian besar dari staf ini adalah anak-anak muda. Ada yang datang dari masyarakat sekitar, ada pula yang mahasiswa dari Jember. Mereka mengikuti berbagai program pelatihan dan direkatkan lewat berbagai kegiatan internal. Hasilnya, kemampuan mereka untuk bicara di depan publik semakin baik dan mereka semakin aktif mengembangkan program divisi masing-masing.
Jika awalnya hanya terpusat di Ledokombo, kini Tanoker juga berkegiatan di desa-desa sekitarnya. Desa Sumber Lesung, Sumber Salak, dan Selateng adalah beberapa di antaranya. Hal ini memang disengaja sebagai upaya Tanoker memeratakan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, utamanya terkait isu buruh migran.
Haris (26), salah satu staf Divisi Event Organizer, berasal dari Desa Sumber Nangka. Ia pernah menyaksikan Festival Egrang sebagai penonton. Melihat anggota panitianya yang sibuk mengatur acara sambil memegang handie talkie, tak urung ia berpikir, “Keren juga mereka. Kapan ya saya bisa pegang alat itu?”
Haris dulunya bekerja sebagai pencari rumput ternak dan membantu tetangga berjualan mi ayam. Kini ia aktif mengelola berbagai kegiatan Tanoker. Banyak hal yang dipelajarinya sejak bergabung pada 2015. “Dulu saya tidak mengerti bahasa Inggris, sekarang sudah paham. Saya juga mengerti prosedur keberangkatan buruh migran. Bagaimana pentingnya persyaratan dan kontrak agar mereka terjamin,” cerita Haris.
Tak Lupa Berdayakan Para Ibu
Tanoker tidak hanya berupaya mengurangi dampak persoalan buruh migran terhadap anak-anak. Divisi khusus bertajuk Tanocraft adalah sebuah unit usaha kerajinan yang mengasuh para perempuan; baik yang pernah menjadi buruh migran maupun yang ditinggalkan pasangannya bekerja ke luar negeri. Tujuannya, agar mereka bisa mandiri dan memiliki sumber penghasilan sehingga tak perlu lagi menjadi buruh migran. Tanocraft berperan sebagai fasilitator.
“Tugas saya sekarang sebagai motivator bagi para ibu. Juga mengorganisasi mereka dan sebagai konsultan unit usaha. Misalnya, membantu mereka membuat Surat Izin Usaha,” papar Sutopo, staf Divisi Tanocraft yang sudah aktif sejak 2014.
Saat ini sudah ada delapan kelompok usaha dalam Tanocraft. Masing-masing beranggotakan 10 orang perempuan yang memproduksi tas, topi, aksesori, serta batik bermotif egrang dan yoyo. Para pendamping di Tanocraft membekali mereka dengan kemampuan manajerial, menyediakan bahan mentah, membantu mengecek kualitas produksi, dan membukakan saluran pemasaran.
Kendala sudah pasti ada. Salah satu yang terbesar adalah mental para ibu. Pada dasarnya, mereka adalah ibu rumah tangga, yang bisa bekerja selama tiga sampai empat jam saja. Agar terbangun komitmen kerja profesional, untuk memenuhi tenggat dari pelanggan, pendamping Tanocraft harus proaktif mencari cara. Salah satu yang dilakukan Sutopo, misalnya, adalah menyediakan bonus ketika ibu-ibu perajin bisa melampaui target.
Kemampuan komunikasi juga menjadi ganjalan. Kebanyakan latar belakang pendidikan mereka belum sampai tingkat SMP, sehingga kurang percaya diri untuk bicara dengan orang-orang dari luar Ledokombo. Namun, ganjalan itu tetap tidak menghalangi kesuksesan mereka dalam berproduksi. Sudah ada kelompok yang berhasil menjual barang kriya sebagai cendera mata pernikahan dan bisa menghasilkan enam ratus ribu rupiah sampai satu juta rupiah setiap bulan.
Bukan Lagi tentang Kriminalitas
Pada awal kedatangan mereka, Farha dan Supohardjo hanya bisa menemukan nama Ledokombo dalam berita-berita tentang kriminalitas dan kemiskinan. Kini tidak lagi. Upaya mereka membangun Tanoker berdampak baik pada citra daerah. Berita-berita seputar Ledokombo kini berkisar tentang prestasi dan penghargaan.
Farha memanfaatkan betul pengalaman lebih dari 20 tahun di berbagai organisasi kemanusiaan dan pemberdayaan perempuan; begitu pula Suporahardjo yang akademisi dan pegiat di bidang lingkungan. Pengalaman dan jejaring mereka memudahkan Tanoker mengajak berbagai pihak menjadi mitra. Sejak awal penyelenggaraan Festival Egrang, mereka melibatkan rekan-rekan peneliti dari berbagai negara untuk menjadi juri festival.
Tanoker juga aktif menggandeng pemerintah dalam kegiatan-kegiatannya. Mulanya Festival Egrang hanya melibatkan kecamatan tempat berlangsungnya acara. Pada 2012, Festival Egrang IV sudah mendapat bantuan dana dari Pemerintah Kabupaten Jember. Selain itu, Pemkab juga mempromosikan Festival Egrang sebagai bagian dari kalender kegiatannya. “Ini bagus. Supaya kami tidak sendirian dan festival ini jadi milik masyarakat,” tutur Supohardjo bersemangat.
Selain lewat situs resmi Pemkab Jember, Festival Egrang dipromosikan dari mulut ke mulut dan lewat media sosial di internet. Cara ini terbukti efektif. Sebuah komunitas egrang dari Belgia bahkan mengajukan diri untuk ikut mengisi Festival Egrang IX tahun ini. Mahasiswa dari berbagai universitas di Jember juga selalu bersemangat untuk terlibat sebagai relawan, yang jumlahnya bisa mencapai 250 orang.
Walaupun demikian, Festival Egrang tetap dijaga sebagai perayaan seni warga lokal. Wargalah yang menjadi penggerak dan penampil utama dalam festival. Keterlibatan warga sampai pada menyiapkan rumah sebagai penginapan dan memasak makanan untuk para pengunjung. Hasil kriya para peserta Tanocraft juga dipasarkan sebagai cendera mata khas.
Pemerintah Daerah Jember kini telah melibatkan Tanoker dalam perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tanoker mengusulkan Jember sebagai kota layak anak, termasuk anak-anak difabel dan mereka yang termarjinalkan. Tanoker dilibatkan dalam gugus tugas pelaksanaan program itu.
Dengan kemajuan-kemajuan yang telah diciptakannya, Tanoker tak berpuas diri. Banyak hal yang ingin mereka benahi. Pengembangan kapasitas SDM, misalnya, belum bisa dilakukan secara sistematis. Kebanyakan staf masih belajar mandiri lewat pengalaman langsung di lapangan. Belum lagi kekurangan sarana, terutama alat-alat mengajar dan transportasi. “Mobil penting untuk kami. Ini kecamatan kecil, jarang ada moda transportasi yang lewat,” mereka berkisah. Dengan sarana yang lebih lengkap, Tanoker berharap bisa mewujudkan visi baru mereka tentang Ledokombo: kampung wisata belajar.
*Artikel “Menjemput Masa Depan dengan Egrang” merupakan bagian dari buku Dampak Seni di Masyarakat terbitan Koalisi Seni Indonesia. Buku bisa dibeli dengan mengirimkan surel ke sekretariat@koalisiseni.or.id.