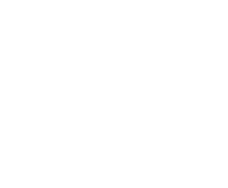Jakarta – “Ilmuwan politik sering menjadikan budaya sebagai residual variable. Ketika berbagai teori tidak bisa menjelaskan suatu fenomena, barulah budaya ditempatkan sebagai penjelasan akhir. Sekarang, kita akan melihat budaya dengan cara pandang berbeda, yakni sebagai modality untuk maju,” ujar Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Philips J. Vermonte membuka Cultural Economics Forum pada 5 September 2019. Pernyataan ini menunjukkan kebudayaan kerap dianggap sebagai hal tersier ketimbang “isu keras” seperti ekonomi maupun politik. Sebagai contoh, apa yang dapat budaya tawarkan terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia? Atau, bagaimana kebudayaan dapat mengurangi angka pengangguran?
Untuk menjelajahi hubungan antara kebudayaan dan ekonomi, Koalisi Seni bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan dan Kedutaan Besar Australia menyelenggarakan acara Cultural Economics Forum di Auditorium CSIS, Jakarta. Pembicara forum ini adalah Prof. David Throsby AO (pakar ekonomi berbasis kebudayaan dari Macquarie University, Australia), Dr. Mari Elka Pangestu (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2011-2014), serta Dr. Hilmar Farid (Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan).
David Throsby memaparkan bahwa kaitan ekonomi dan kebudayaan yang lebih dikenal saat ini adalah konsep Ekonomi Kreatif, yang menempatkan kreativitas sebagai motor inovasi untuk menghadirkan pemikiran baru. Throsby berpendapat rangsangan kreatif ini berasal dari produk kebudayaan yang memberi makna dan memiliki dimensi simbolik. Inspirasi yang diperoleh dari konsumsi produk budaya seperti musik, sastra, hingga seni pertunjukan dapat diteruskan lagi ke sektor ekonomi kreatif yang lebih pragmatis seperti periklanan, desain, kriya, hingga permainan elektronik.
“Karena produk kebudayaan memberikan banyak manfaat selain menjadi komoditas bernilai jual, kita perlu menyikapinya secara berbeda pula. Seni dan budaya menjadi sebuah barang publik (public good) yang perlu difasilitasi pemerintah apabila tidak dapat ditopang mekanisme pasar,” tutur Throsby.
Senada dengan Throsby, Mari Elka Pangestu menjelaskan sektor ekonomi kreatif yang tengah dikembangkan pemerintah sangat bertumpu pada kebudayaan. Kearifan lokal dapat dipadukan dengan teknologi dan inovasi, seperti pada kasus game horor Dreadout yang mengangkat cerita hantu dari berbagai daerah di Indonesia. Dimensi inilah yang membuat ekonomi kreatif tidak dapat dipisahkan dari nation branding maupun soft power.
“Kekayaan Intelektual menjadi currency dari perekonomian kini. Saat Eko Nugroho mendesain untuk edisi terbatas Louis Vuitton, nilainya menjadi tinggi karena jumlahnya terbatas, sedangkan merek dan senimannya terkenal pula,” ucap Mari. “Kita perlu memetakan masalah yang perlu dipecahkan, seperti yang dilakukan Koalisi Seni. Bagaimana menjaga sumber daya kreatif, atau model bisnis seniman?”
Menurut Hilmar Farid, sumbangsih penting dari Throsby adalah memberi perbedaan antara nilai ekonomi dan nilai budaya. Tantangan berikutnya ialah menerapkan alat ukur tepat terhadap nilai budaya yang tidak tampak tersebut. Saat ini, pemerintah sedang merancang Indeks Pembangunan Kebudayaan sebagai kerangka acuan untuk mengukur intervensi dan produk yang dihasilkan. Indeks ini memotret tujuh hal, yakni: ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, kebebasan ekspresi, budaya literasi, dan kesetaraan gender.
“Dengan indeks ini, kita dapat melihat apa kontribusi—sebagai contoh—panggung kesenian terhadap ketahanan sosial budaya. Apakah keberadaan panggung kesenian dapat mengubah sikap seseorang terhadap tetangga yang memiliki agama berbeda, misalnya,” kata Hilmar.

Audiens forum menanggapi gagasan ekonomi berbasis kebudayaan ini dengan antusias. Suara kritis pun tetap hadir, seperti pertanyaan mengenai batas kontrol pemerintah ketika mendanai seni budaya, juga cara menentukan seni yang masuk dalam kategori barang publik (public good).
“Sudah tidak zaman lagi bagi negara untuk mendefinisikan budaya dan seni. Sekarang, negara hanya terlibat sebagai fasilitator,” ujar Hilmar menanggapi.
Untuk menjelaskan tentang konsep barang publik, Throsby menceritakan anekdot mengenai orkestra Tasmania yang nyaris dibubarkan. “Orkestra telah menjadi simbol penting dan bagian dari identitas Tasmania. Warga memprotes rencana pembubaran, bahkan rela menyisihkan sebagian pajak mereka untuk mendanai orkestra tersebut,” ucapnya menjelaskan.
Sementara itu, Mari menekankan budaya dapat menciptakan nilai ekonomi dalam berbagai bidang. Maka, cara mengembangkan modal budaya menjadi hal krusial. “Apresiasi menjadi sangat penting, karena inilah yang menciptakan nilai. Kita perlu mengapresiasi proses produksi pula. Biasanya, donor hanya mau membiayai pertunjukan, bukan prosesnya. Untuk itu, negara harus bisa menjustifikasi pendanaan, bahwa ada barang publik yang diperjuangkan di sini,” katanya.
Pada keesokan harinya, Throsby memberikan kuliah umum yang mengulas lebih dalam tentang ekonomi berbasis kebudayaan. Dihadiri sekitar 200 orang pegiat seni budaya dan akademisi, kuliah umum tersebut disertai sesi tanya jawab interaktif yang dipandu oleh Hilmar Farid.
Menyadari tingginya potensi ekonomi berbasis kebudayaan, CSIS telah menyatakan komitmennya untuk bekerja sama dengan Koalisi Seni melanjutkan rangkaian acara ini. Silakan simak website dan media sosial Koalisi Seni untuk mendapatkan kabar tentang kegiatan ekonomi berbasis kebudayaan berikutnya. (Eduard Lazarus)
Materi presentasi forum dan kuliah umum beserta infografis, graphic recording, lembar fakta, dan siaran pers dapat diunduh di bit.ly/culturaleconomics.