*Tulisan ini adalah bagian pertama dari dua tulisan yang saling berkaitan tentang permasalahan kepemilikan master rekaman, dan gugatan uji materiil PT Musica Studio ke Mahkamah Konstitusi
Kepemilikan Master Fonogram
Dalam ranah skena independen, kebanyakan band seangkatan band saya (Efek Rumah Kaca atau ERK) mengerjakan banyak hal terkait produksi sebuah album secara mandiri atau bersama label-yang biasanya digerakkan oleh orang yang sama atau masih dalam lingkaran pertemanan, yang kecil dan akrab.
Mulai dari latihan di studio, mengaransemen, rekaman hingga mixing & mastering dikerjakan sendiri. Tak berhenti sampai tahap produksi, kami kerap memasarkan dan mendistribusikannya sendiri juga. Saling dukung antar teman/band dengan hadir menyaksikan pertunjukan dan membeli berbagai produk fisik rilisan mereka ternyata menjadi energi yang dahsyat dalam menggerakan skena. Apa yang terjadi di luar skena, sebodoamatlah, tak relevan.
Dalam liga yang berbeda, band-band yang tergabung dengan perusahaan rekaman besar, ketika memproduksi musiknya membutuhkan modal yang besar. Sehingga, mereka memerlukan peran produser dan eksekutif produser. Kehadiran produser dan label tersebut bisa membantu mewujudkan mimpi para musisi untuk membuat rekaman yang diinginkan dan memasarkannya ke skala nasional, bahkan internasional.
Namun, konsekuensi dari keluarnya modal yang cukup besar dari para produser tersebut ternyata cukup sesak. Musisi harus merelakan aset kekayaan intelektualnya yaitu master rekaman atau fonogram-jika mengacu ke istilah Undang Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 (UU Hak Cipta)-selama waktu tertentu, untuk dikuasai oleh para produser. Hal tersebut, tidak terjadi pada kebanyakan band independen, yang rerata menguasai kepemilikan atas master rekaman album-album mereka.
Mendadak Industri
Perubahan pola konsumsi musik yang terjadi lima sampai tujuh tahun belakangan ini, yaitu dengan berkembangnya format musik digital disertai dengan bertumbuhnya industri pendukungnya, ternyata mengaburkan dikotomi antara “arus utama” dan “pinggiran.” Dalam ranah digital yang tanpa sekat, pergerakan musik yang didukung oleh modal besar (baca: arus utama) bercampur aduk dengan pergerakan musik dengan modal yang lebih kecil namun mandiri, dalam satu kolam yang sama. Semua belajar untuk mencari formula yang tepat dalam memproduksi dan mengkonsumsi musik.
Pergeseran dari industri musik konvensional menuju industri musik digital ini membuat band-band yang sebelumnya cukup berjarak dengan industri, kemudian menjadi bagian dari industri itu sendiri. Mendadak Industri, jika boleh mencomot istilah yang awalnya dipopulerkan oleh film Mendadak Dangdut.
Dengan segala infrastruktur yang sudah ada dan tersedia di ranah digital, yang dulunya hanya memberikan wadah, ternyata sekarang juga memberikan penghasilan yang “menjanjikan“ atau istilah populernya “cuan.“ Hal ini tentu saja disambut dengan sumringah oleh teman-teman dari skena pinggiran (saya dengan enteng saja mengganti-ganti istilah independen dan pinggiran, kira-kira miriplah maksudnya).
Apalagi, banyak dari band independen, memang sejak awal sudah lihai berkeliaran di jagat maya. Mereka sejak awal berjejaring, mencari info panggung terkini dan memasarkan musiknya di sana. Hanya sebagian kecil saja dari musisi/band yang ada sekarang yang tidak tersambung atau tersedia di platform seperti Spotify, Youtube, Apple Music, Bandcamp atau situs sejenis. Selebihnya, terjun bebas ke dalam berbagai platform tersebut.
Salah satu hal yang penting untuk dipahami dengan ikut terjunnya musisi/band ke dalam platform tersebut adalah hak cipta. Berbagai platform tersebut menyediakan, menyisihkan dan membayarkan berbagai royalti bagi musisi/band yang lagunya diputar atau diunduh di kanal mereka sesuai dengan ketentuan hak cipta yang mengikat platform tersebut.
Kipas-kipas Pemilik Master Rekaman
Membicarakan hak cipta merupakan upaya yang pelik, sering dibicarakan namun tak mudah dipahami alias ruwet. Saya sendiri masih belajar tentang itu sampai sekarang. Berdasarkan pengalaman pribadi, penjelasan di bawah ini bisa memberikan sedikit gambaran tentang apa saja yang termasuk dalam hak cipta.
Secara sederhana, menurut UU Hak Cipta, hak cipta terdiri dari dua: hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi terdiri dari dua juga: hak penggandaan pemilik master fonogram/rekaman (biasa disebut mechanical rights) dan hak mempertunjukan/mengumumkan (biasa disebut performing rights). Hak mengumumkan terdiri dari dua juga: hak cipta dan hak terkait. Hak terkait terdiri dari tiga: produser rekaman, pelaku pertunjukan dan lembaga penyiaran.
Hak-hak di atas adalah hak yang muncul ketika satu lagu diputar (digandakan dan diumumkan) pada suatu platform. Hak lain yang juga dimiliki pencipta lagu adalah hak atas penerbitan lagu (buku notasi lagu) dan hak adaptasi/transformasi (dikenal juga dengan hak sinkronisasi). Untuk mengetahui definisi tentang masing-masing istilah tersebut di atas, bisa merujuk ke sumbernya langsung yaitu UU Hak Cipta.
Pada artikel sebelumnnya, Endah Widiastuti, sang Ratu Pamulang membahas tentang hak mengumumkan/menyiarkan (performing rights) dan turunannya. Yang ingin saya tambahkan sedikit dalam tulisan ini adalah hak penggandaan master fonogram (mechanical rights) karena relevan dengan gugatan PT LAS eh maksud saya PT Musica Studio ke Mahkamah Konstitusi baru-baru ini.
Berdasarkan pencarian di internet, Manatt, sebuah firma teknologi digital memberikan ilustrasi yang mudah dimengerti tentang persentase pembagian royalti dari setiap pemasukan yang didapatkan oleh Digital Service Provider (DSP) Spotify dan Apple Music.
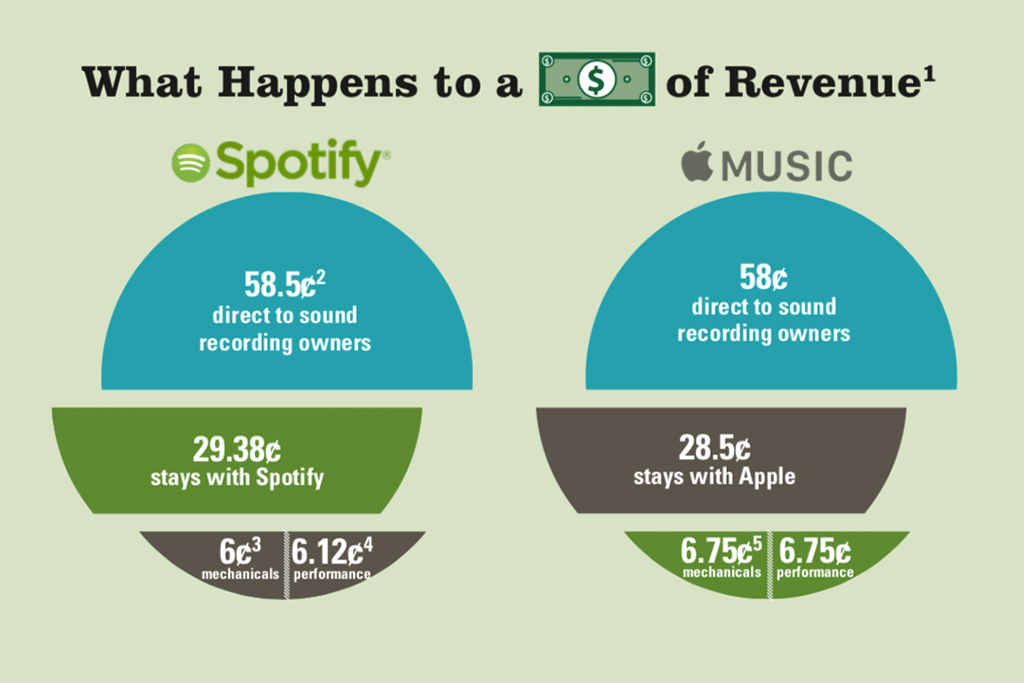 Sumber: https://www.manatt.com/Manatt/media/Media/PDF/US-Streaming-Royalties-Explained.pdf
Sumber: https://www.manatt.com/Manatt/media/Media/PDF/US-Streaming-Royalties-Explained.pdf
Dari ilustrasi di atas, terlihat bahwa porsi terbesar didapatkan oleh para pemilik master rekaman, yaitu rerata lima puluh delapan persen (58%) atau hampir sepuluh kali lipat dari hak cipta maupun hak terkait yang kurang lebih hanya sebesar enam persen (6%).
Masih menurut Manatt[1], dari 58 sen yang didapatkan produser label sebagai pemilik master, hanya sekitar 9 sen atau 16-18% yang dibagikan kepada musisinya. Sisanya, setelah dikurangi biaya pemungutan royalti, masuk kantong pemilik master. Sedangkan produser dari label kecil biasanya memberikan 50% dari pendapatan tersebut ke musisinya, atau kurang lebih sebesar 29 sen. Yang lebih besar porsinya tentu saja musisi yang memiliki master rekamannya sendiri. Setelah dipotong biaya distribusi, mereka akan mengantongi 90% dari pendapatan tersebut atau kurang lebih sebesar 52 sen.
Selamat kipas-kipas musisi pemilik master rekaman.
Jual Putus
Lalu, siapakah yang paling sial? Sudah pasti musisi yang tidak mendapatkan royalti yang mengalir sampai jauh itu.
Mengapa bisa begitu? Hal itu bisa terjadi karena biasanya pada saat perjanjian kerja sama produksi lagu/album, musisi atau band tersebut setuju untuk menggunakan sistem sold flat atau jual putus. Sehingga jika album tersebut laku keras, maka tak perlu ada kompensasi tambahan dari pemilik master atas rekaman tersebut kepada musisi maupun pencipta lagu.
Apakah perjanjian jual putus itu sah? Selama memenuhi empat syarat sahnya perjanjian yaitu kesepakatan, kecakapan, objek yang diperjanjikan dan sebab yang halal, maka perjanjian jual putus itu sah di mata hukum. Jika perjanjian itu sah, mengapa diributkan? Ternyata pada pelaksanaanya, banyak musisi/band yang menyesali proses jual putus tersebut dengan berbagai macam alasan.
Dahulu, yang tidak dahulu-dahulu amat, kesempatan rekaman/merekam lagu hanyalah milik orang-orang yang punya modal, karena biayanya mahal. Sehingga sulit bagi musisi/band untuk bisa rekaman atau mendapatkan kontrak rekaman. Oleh karenanya, ketika label atau produser menawarkan kontrak rekaman, saking ngebetnya rekaman, musisi ambil sikap pragmatis saja: setuju! Yang terbayang oleh mereka hanya kenikmatan merekam lagu, lalu lagu mereka diputar di radio/tv dan mereka bisa unjuk aksi di panggung.
Sikap pragmatis/ngebet musisi tersebut membuat posisi tawar produser jadi jauh lebih tinggi dibandingkan posisi tawar musisi/band. Situasi ini kemudian menyebabkan kontrak yang dibuat akan berat sebelah, dengan produser/label sebagai penerima keuntungan terbanyak.
Bertahun-tahun kemudian barulah para sang musisi menyadari kerugiannya. Akibatnya, sering saya mendengar desas desus semacam ini: musisi senior A, tak mendapatkan kompensasi tambahan atau royalti, padahal albumnya laku keras.
Jualan Lagu is Everyday Life?
Saya ada sedikit cerita yang cukup relevan. Mundur sejenak ke akhir 80-an dan awal 90-an, ketika masih muda belia, saya mengantar teman ke wilayah Kota Tua. Dari Ciputat rasanya jauh sekali. Pada malam sebelumnya, ia menginap di rumah sambil membawa kaset kosong dan taperekaman, seperti yang biasa dibawa oleh wartawan. Malam itu, menggunakan gitar akustik saya, dia merekam lagu yang sudah dibuatnya di rumahnya.
Ternyata, lagu yang direkam itu, akan dijual pada sebauh label rekaman yang berkantor di Mangga Dua.
“Jualan lagu???? Ikut dong.” Saking anehnya mendengar orang menjual lagu, saya menawarkan diri untuk ikut.
Keesokan harinya, ketika kami sampai di kantor label yang dituju (pada saat itu, banyak label rekaman berkantor di area perkantoran itu), saya lihat beberapa orang berdiri di luar, menunggu dipanggil oleh orang yang duduk di dalam. Mau apa mereka? Ya betul, mencari peruntungan dengan menjual lagu.
Ketika teman saya dipanggil ke dalam, saya sempat mengintip ke samping kanan di mana orang label tersebut duduk, menumpuk kaset rekaman yang terlihat sejenis dengan yang teman saya bawa. Jika kaset-kaset itu adalah kaset demo lagu-lagu yang dijual, berarti jualan lagu is everyday life di sana, saat itu.
Saya sempat bertanya ke teman saya, biasanya satu lagu yang enak dan berpotensi meledak, yang diciptakan oleh pencipta lagu yang tak terkenal, paling tinggi dibeli dengan harga berapa? Ia menjawab “mungkin sekitaran Rp.350.000, tanpa nama pencipta,” yang artinya, lagu tersebut akan diakui milik orang lain, atau hilang hak moral penciptanya.
Bagi anak sekolah menengah pertama, yang hari-harinya diisi dengan nongkrong gitaran, kemungkinan mendapatkan uang tambahan dari jualan lagu ibarat sambal berdiang masak nasi. Tahu artinya? Ok, pepatah yang lebih akrab, sambal menyelam minum air.
Dari cerita di atas, saya ingin menebalkan bahwa praktik jual putus-bahkan hingga hak moral penciptanya dicabut, sehingga lagu sepertinya bukan lagi karya kreatif yang dilindungi hak ciptanya tapi lebih mirip benda yang diperjualbelikan seperti biasa-sudah menjadi pola dalam industri musik, saat itu. Kemudian, seperti cerita musisi senior di atas, korban pun berjatuhan.
Reversionary Rights
Saking seringnya terdengar desas desus tentang banyaknya korban lagu yang dijual putus dan ternyata meledak dan tidak ada kompensasi tambahan bagi penciptanya, akhirnya pemerintah memberikan proteksi dengan menambahkan pasal reversionary rights pada UU Hak Cipta tahun 2014, yang mana hal tersebut tidak ada pada UU Hak Cipta tahun 2002.
Singkatnya, reversionary rights adalah hak negosiasi ulang bagi karya cipta dan karya pelaku pertunjukan yang menggunakan sistem jual putus, jika karya tersebut sudah berumur lebih dari dua puluh lima tahun. Jadi, tahun ke-26 sampai tahun ke-50, para pencipta dan pelaku pertunjukan akan mendapatkan royalti sesuai kesepakatan bersama. Jika tidak ada kata sepakat, pihak pemilik master tidak bisa memanfaatkan hak ekonomi tersebut alias master mangkrak. Pasal-pasal yang berkaitan dengan reversionary rights adalah pasal 18, 30 dan 122 UU Hak Cipta.
Karena reversionary rights merupakan hal baru, tak heran masih banyak musisi atau pencipta lagu yang belum tahu, apalagi memanfaatkan hak tersebut. Kabar terkini, Candra Darusman, pencipta lagu kawakan, berkat reversionary rights ini berhasil menegosiasikan ulang lagu-lagunya yang dijual putus dengan Musica dan Prosound. Akhirnya pencipta kembali mencicipi manisnya royalti. Semoga hal yang sama bisa dinikmati oleh pencipta lagu lainnya.
Biar bisa kipas-kipas seperti para musisi yang memiliki master rekamannya, musisi senior mesti segera memanfaatkan reversionary rights ini. Mumpung masih ada, sebelum nanti hak tersebut coba direnggut dari kalian!
Penulis: Cholil Mahmud, vokalis/gitaris Efek Rumah Kaca dan Pandai Besi
Sumber: https://pophariini.com/master-rekaman-milik-sendiri-harga-mati-oleh-cholil-mahmud/




