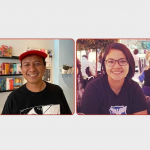Eduard Lazarus, Peneliti Kebijakan Seni dan Budaya, Koalisi Seni
Empat bulan setelah kasus Covid-19 pertama di Indonesia pada Maret, pemerintah akhirnya menetapkan kondisi New Normal. Berbagai kegiatan masyarakat yang sempat mandek selama berbulan-bulan—khususnya akibat Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) yang melarang kumpulan orang dalam jumlah besar di muka publik—kini diizinkan bergulir kembali dengan sejumlah aturan baru. Norma sosial yang selama ini diterapkan masyarakat secara sporadis selama pandemi (seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mempertimbangkan kondisi tubuh sebelum bepergian), sekarang menjadi aturan yang resmi diterapkan pemerintah melalui protokol kesehatan di berbagai sektor.
Bagi sektor kesenian, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah mengeluarkan protokol pada 2 Juli 2020—dapat diunduh di sini—mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19 di bidang kebudayaan dan ekonomi kreatif. Protokol setebal 49 halaman ini berisi sejumlah aturan komprehensif mengenai penyelenggaraan layanan museum, taman budaya, sanggar, bioskop, cagar budaya, pertunjukan seni hingga produksi audiovisual. Selain itu, pada protokol ini tercantum pula sebuah formulir skrining mandiri yang dapat diterapkan tiap orang untuk mengukur tingkat risiko mereka mengidap COVID-19 sebagai pertimbangan sebelum beraktivitas di publik.
Perlu dicatat bahwa aturan-aturan dalam protokol ini bersifat teknis dan sangat rinci. Pada protokol mengenai pertunjukan seni, misalnya, terdapat aturan mengenai tata letak ruang pertunjukan (Poin E2 C2e: “pemisahan antar-kelompok pengunjung dalam lingkaran-lingkaran berdiameter maksimal tiga meter, dengan jarak antar-lingkaran satu koma lima meter”), hingga aturan-aturan yang dapat terdengar normatif (E2 C3a9: “konsumsi perlu dijamin kebersihan dan higienitasnya”). Pada produksi audiovisual, protokol ini bahkan mengatur perkara tata rias (E2 D2b5: “penggunaan riasan atau pulasan wajah dilakukan oleh masing-masing orang, upayakan menggunakan peralatan rias pribadi”) hingga properti produksi, seperti rambut palsu (E2 D2b7: rambut palsu dan kuas riasan harus selalu dibersihkan dengan disinfektan setelah pemakaian”).
Sifat komprehensif protokol ini dalam mengatur berbagai aspek dalam proses kegiatan seni perlu diapresiasi. Di atas segalanya, kerincian tersebut menunjukkan bahwa protokol ini disusun melalui proses riset mengenai seluk-beluk kegiatan bidang kebudayaan dan industri kreatif. Tantangan berikutnya berkaitan dengan implementasi protokol tersebut: bagaimana cara memastikan bahwa masyarakat, khususnya pegiat seni menerapkannya dengan baik? Riset yang dilakukan oleh PolGov UGM, misalnya, menemukan bahwa wacana pemberitaan New Normal masih “terpusat di pemerintah”, alias masih berupa isu elit pemerintah yang belum dikontekstualisasikan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.
Baiknya, dalam protokol ini tertulis pula bahwa kegiatan kebudayaan dan ekonomi kreatif hanya dapat diselenggarakan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah. Dengan demikian, setiap daerah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu kesanggupan mereka dalam menyelenggarakan kegiatan publik. Selain itu, Surat Keputusan Bersama ini juga mengamanatkan bahwa tiap kelompok sasaran (pengelola ruang seni, pertunjukan seni, atau produksi audio-visual) perlu membuat protokol turunan yang spesifik untuk ranah masing-masing.
Kontekstualisasi protokol berdasarkan daerah dan ranah kegiatan seni, dengan demikian, menjadi kunci agar New Normal bagi sektor kesenian berjalan dengan baik dan justru tidak menimbulkan permasalahan baru. Bagaimana proses ini, dalam kenyataannya, berlangsung di lapangan?
Salah satu daerah yang benar-benar merasakan imbas dari pandemi Covid-19 adalah Bali: pada tahun 2019, kontribusi pariwisata Bali mencapai Rp75 Triliun atau 28.9% dari keseluruhan devisa pariwisata nasional. Ketergantungan Bali terhadap sektor pariwisata berpotensi membuat perekonomian provinsi tersebut terpuruk selama pandemi, apalagi dengan larangan wisatawan mancanegara hingga bulan September. Sementara itu, liputan The Guardian mengabarkan bahwa kapasitas rumah sakit di Bali untuk menangani pasien Covid-19 sudah mencapai kapasitas maksimal.
Perbincangan dengan Rudolf Dethu, anggota Koalisi Seni dan Co-Director Rumah Sanur Creative Hub, menunjukkan adanya ambiguitas dari berbagai tingkat Pemerintah Bali—seperti Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kota Denpasar, dan Pemerintah Kabupaten Badung—dalam mengatasi pandemi Covid-19. Secara umum, berbagai usaha sektor pariwisata seperti restoran, kafe, bar dan klub sudah beroperasi kembali. Hanya saja, tidak semuanya menerapkan standar protokol kesehatan dengan baik: ada sejumlah tempat usaha yang mengabaikan protokol sama sekali, maupun hanya menerapkan protokol seadanya (menerapkan jarak antar pengunjung, namun mengabaikan jarak antar pengunjung ketika sudah duduk di satu meja). Dethu menyebutkan Hard Rock Cafe di Kuta, Kabupaten Badung, sebagai salah satu tempat yang menjalankan protokol dengan ketat—bahkan melakukan sejumlah rekayasa canggih di lokasi seperti meletakkan perangkat untuk membuka pintu dengan kaki.
Dethu, sebagai orang yang telah bertahun-tahun berkecimpung dalam skena musik, aktivisme, dan industri kreatif Bali, menekankan bahwa “membuat 200 protokol pun tidak akan berpengaruh apabila tidak ada yang memantau pelaksanaannya”. Berdasarkan pengamatan Dethu, sejauh ini belum ada pihak yang mendatangi tempat usaha industri kreatif untuk memastikan bahwa prosedur kesehatan diterapkan dengan baik: satu-satunya kasus yang sempat ia ceritakan adalah ketika polisi mendatangi sebuah klub untuk mengingatkan bahwa mereka beroperasi melewati jam malam yang ditentukan.
Kendati penerapan protokol keamanan yang jauh dari konsisten di tempat-tempat hiburan, Dethu mengatakan bahwa berbagai musisi, yang kerap menggantungkan penghidupan mereka dengan tampil di tempat-tempat tersebut, masih belum tampil juga. Namun, hal ini lebih disebabkan bahwa keberadaan musisi tidak dianggap hal primer bagi pengelola venue, yang berupaya memangkas pengeluaran selama pandemi. Ketika pengelola memutuskan untuk mulai mementaskan kembali musisi pun, tampaknya mereka akan memulai dengan set akustik alih-alih full-band.
Ketidakpastian mengenai kondisi pariwisata di Bali inilah yang membuat banyak pekerja sektor kreatif, termasuk seniman, memutuskan beralih ke pekerjaan lain terlebih dahulu, dari menjual makanan hingga kembali bertani dan menangkap ikan. Selaku Creative Hub, Rumah Sanur sendiri kini mengalihfungsikan diri sebagai tempat penyaluran bantuan bahan pokok bagi seniman dan orang lain yang membutuhkan. Padahal, jelas Dethu, Rumah Sanur sebelumnya bisa menyelenggarakan lebih dari 400 acara tiap tahunnya. Untuk sementara, mereka mematok baru akan melaksanakan aktivitas kembali pada bulan Agustus.
Apabila kondisi di Bali ditandai dengan pemantauan yang minim dan penerapan protokol kesehatan yang inkonsisten, hal yang cukup berbeda terjadi di Kota Malang. Pada masa awal pandemi, Pemerintah Kota Malang mengalokasikan insentif untuk masyarakat perekonomian rendah yang membutuhkan bantuan. Untuk menjangkau kelompok seniman dan budayawan, Pemkot Malang bekerja sama dengan Dewan Kesenian Malang, yang melakukan pendataan langsung dengan mendatangi kediaman para seniman. Yuyun Sulastri, anggota Koalisi Seni dan Dewan Kesenian Malang yang turut melakukan proses pendataan ini, mengabarkan bahwa bantuan sudah dicairkan selama dua kali dan tengah menunggu termin pencairan ketiga—dan terakhir—untuk bulan Juli.
Kerja sama antara kelompok seniman dan pemerintah ini terus berlangsung hingga masa New Normal. Ketika Dewan Kesenian Malang kembali membuka gedung mereka untuk aktivitas publik, mereka melakukan pencatatan rinci akan semua orang yang datang ke lokasi tersebut—meliputi nama lengkap, alamat, nomor ponsel dan suhu badan pada waktu kedatangan—dan mengirimkannya secara rutin ke Gugus Tugas Covid-19 Kota Malang untuk keperluan contact tracing. Pengunjung dengan suhu badan melampaui 37.3 derajat celcius diminta—kendati dengan penuh perasaan sungkan—untuk tidak memasuki gedung Dewan Kesenian Malang terlebih dahulu. Meski demikian, pertunjukan dengan jumlah orang banyak belum dihelat. Sebaliknya, mereka hanya menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kecil seperti lokakarya hingga pelatihan tari.
Gedung Dewan Kesenian Malang memang tidak menyediakan rekayasa ruang yang canggih—tidak ada alat khusus untuk membuka pintu menggunakan kaki—namun, hal mengesankan dari praktik mereka adalah pengeluaran biaya yang minim untuk melaksanakan protokol-protokol kesehatan standar. Stok hand sanitizer yang mereka miliki, misalnya, diperoleh dari Gugus Tugas Covid-19 Kota Malang yang sempat mereka bantu sebagai relawan, sementara termometer tembak (thermogun) dan face shield untuk pelatihan tari didapatkan melalui sumbangan pihak lain. Bantuan-bantuan kecil macam ini, setidaknya, membuat mereka tidak perlu memikirkan pengeluaran ekstra untuk melaksanakan kegiatan seni kembali.
Menurut Yuyun, kemudahan ini membuat mereka dapat memikirkan bagaimana cara membagikan manfaat penyelenggaraan kegiatan seni kembali ke berbagai seniman. Salah satunya adalah dengan melakukan semacam “arisan kursus”, dimana berbagai pengajar tari modern mengumpulkan murid-murid mereka jadi satu dan mengajar mereka secara bergantian. Di tengah-tengah kepungan pandemi, kerjasama a la mutual aid society terbukti dapat meringankan—kendati tidak menyelesaikan seluruh masalah.
Berkumpulnya seniman untuk menyiasati pandemi tidak hanya terjadi berdasarkan basis kewilayahan, namun dapat juga berupa kerjasama sektor seni dalam skala nasional, bahkan internasional. Amelia Hapsari, Program Director In-Docs dan anggota Koalisi Seni berpendapat bahwa aturan mengenai pembuatan dokumenter melalui protokol pemerintah—yang termaktub dalam Protokol Produksi Audiovisual dengan Lokasi Tidak Terkontrol—sudah cukup rinci. Meski demikian, ia sendiri selama ini sudah berpegang pada dokumen asesmen risiko pembuatan film dokumenter yang diluncurkan oleh Sundance Institute. Panduan ini tidak mengatur teknis pembuatan film dokumenter yang aman layaknya protokol Kemendikbud dan Kemenparekraf, melainkan memberi sejumlah poin yang perlu diperhatikan pembuat film dokumenter ketika produksi: apakah mereka siap dengan skenario terburuk, seperti terjadinya lockdown wilayah dan kru terpaksa menetap di lokasi produksi melampaui jadwal yang direncanakan? Sanggupkah para kru melampaui isolasi mandiri selama 14 hari sebelum dan setelah produksi, tanpa bertemu dengan keluarga dan orang-orang terdekat mereka?
Secara luas, panduan Sundance Institute memberi tiga pertanyaan kunci yang perlu dipikirkan oleh pembuat film dokumenter. Pertama, apakah film dokumenter ini benar-benar harus diproduksi selama pandemi? Apakah isu yang hendak diangkat dalam film ini begitu mendesak dan melayani kepentingan publik (public interest) sehingga produksi tetap harus dilakukan, kendati semua risiko yang ada?
Kedua, sebesar apa risiko dari produksi film bagi kru, keluarga mereka, hingga subjek dokumenter tersebut? Sebagai contoh, masyarakat adat—terutama yang selama ini memiliki kontak terbatas dengan orang-orang lain—memiliki risiko lebih tinggi dalam pandemi karena sistem imun yang belum kebal terhadap berbagai penyakit dan akses fasilitas kesehatan yang seringkali tidak memadai. Hal inilah yang membuat sejumlah masyarakat adat, seperti Komunitas Adat Enggros di Abepura, Papua, menutup akses ke Wilayah Adat mereka.
Ketiga, bagaimana cara untuk mengorganisir produksi agar berlangsung seaman mungkin? Hal ini meliputi pertimbangan mengenai masyarakat di lokasi produksi—akankah kehadiran kru dipandang sebagai hal yang mengancam keselamatan mereka?—hingga anjuran-anjuran untuk sebisa mungkin mengambil gambar di luar ruangan tertutup, menjaga jarak ketika wawancara dengan narasumber, serta membawa kru seminimal mungkin.
Pendekatan Sundance Institute ini memberi gambaran yang lebih luas ketimbang protokol yang mengatur panduan teknis. Pertama, panduan untuk menilai risiko penyelenggaraan kegiatan seni sejatinya menunjukkan bahwa tidak ada protokol yang dapat seratus persen menjamin keamanan dalam melakukan aktivitas seni. Kesadaran ini, lebih jauh lagi, menuntut sektor-sektor yang berbeda dalam kesenian untuk melakukan refleksi lebih dalam akan cara mengoptimalisasikan manfaat mereka bagi masyarakat, serta meninjau kembali praktik-praktik yang sudah saatnya diubah. Menurut Amelia, salah satu isu mendesak yang mengemuka di kalangan komunitas dokumenter internasional adalah menyebarluaskan kemampuan membuat dokumenter agar tidak hanya dimiliki orang-orang tertentu; bahwa praktik mendatangi negara atau wilayah yang berbeda untuk menceritakan kisah masyarakat yang berbeda bukan hal yang seharusnya dapat diterima lagi.
Pertimbangan-pertimbangan mengenai dimensi etika dan substansi ini tidak termaktub dalam protokol pemerintah, yang memang hanya mengatur hal-hal teknis. Ini tentu bukan berarti bahwa protokol pemerintah merupakan hal yang buruk.
Namun, penerapan protokol perlu disesuaikan dengan berbagai tantangan spesifik dalam sektor kesenian dan wilayah yang berbeda. Pemerintah daerah perlu diajak berdialog memikirkan siasat bersama, termasuk mengenai cara produksi karya yang paling minim risiko tapi tetap menjadi wadah bagi ekspresi banyak orang. Saat semua pihak ikut serta urun beban, masa pandemi semoga jadi sedikit lebih tertahankan.