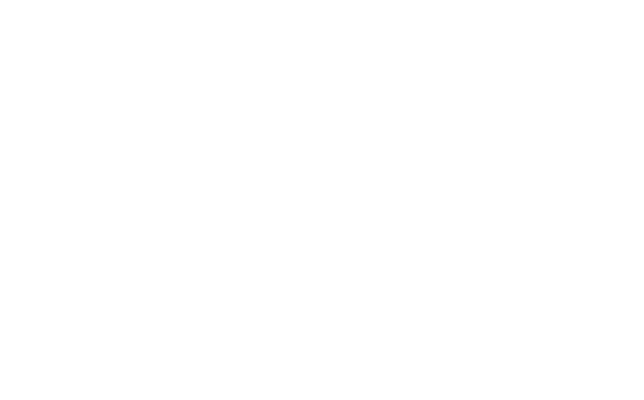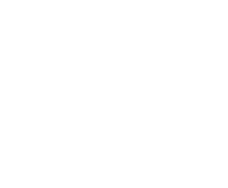Temu Seniman Perempuan di Mataram pada Mei 2016 mengungkap beberapa hambatan perempuan dalam berkesenian, berikut dengan pilihan strategi menghadapinya.
Mataram menjadi tempat yang dipilih oleh Koalisi Seni Indonesia untuk menyelenggarakan Temu Seniman Perempuan seri pertama. Bekerjasama dengan Komunitas Akar Pohon, Pabrikultur, dan Komunitas Pasir Putih, sebanyak 25 peserta diundang ke forum ini. Mereka adalah para seniman perempuan yang berasal dari tujuh kota di Indonesia, yaitu Palu, Makassar, Kupang, Pekanbaru, Jakarta, Yogyakarta, dan Mataram.
Pada pelaksanaannya, acara ini dibagi dalam dua hari. Hari pertama adalah sesi presentasi dan diskusi dengan tema “Perempuan dan Seni”. Kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke Bank Sampah NTB Mandiri di daerah Ampenan pada hari kedua. Saat sesi presentasi dan diskusi itulah beberapa hambatan perempuan dalam berkesenian terungkap, tentu dengan pilihan strategi menghadapinya.

Salah satunya adalah permasalahan terkait ruang gerak perempuan dalam berkesenian yang seringkali dibatasi oleh stigma masyarakat. “Saya sering disebut pekerja seks komersil oleh masyarakat juga bahkan oleh keluarga sendiri karena sering pulang malam. Padahal, saya pulang malam karena latihan teater,” ujar Linda R. Tagie, dari Komunitas Teater Perempuan Biasa. Kondisi yang hampir sama pun terjadi di Mataram.
“Kalau di Mataram, perempuan tidak boleh pulang malam. Bahkan, di beberapa daerah, kalau masyarakat melihat ada perempuan yang sedang bersama laki-laki pada malam hari, mereka akan langsung dinikahkan. Jadinya perempuan sulit berkesenian ataupun menonton pertunjukan seni sampai malam,” kira-kira ujar Etika Lailatul Rahmah, dari Komunitas Pasir Putih.

Kondisi ini membuat perempuan yang bekerja sebagai seniman memiliki beban ganda. Selain memikirkan permasalahan di sektor kesenian, mulai dari akses dana ke pemerintah hingga tata kelola lembaga seni, perempuan pun mesti memikirkan posisinya sebagai perempuan. Beban yang tak dimiliki oleh laki-laki. “Kebanyakan perempuan yang sudah menikah tidak melanjutkan berkarya sebagai seniman karena energinya sudah habis melakukan tugas perempuan di keluarga dan masyarakat,” ujar Ismawati dari Komunitas Akarpohon NTB.
Tidak hanya mendiskusikan tentang permasalahan yang dialami, strategi menghadapinya pun dibicarakan. Terkait stigma, Linda memiliki strateginya sendiri. “Kalau saya, saya tunjukan hasil saya pulang malam yaitu karya pertunjukan saya. Saya kasih gratis tiket VIP menonton pertunjukan saya untuk mereka yang menganggap saya pekerja seks komersil,” ujarnya. Berbeda lagi dengan Etika.

“Beberapa waktu lalu Komunitas Pasir Putih mengajak serta masyarakat untuk ikut dalam kegiatan seni yang kami bikin. Waktu itu nama acaranya Bangsal Menggawe. Ada sekitar 5000 warga yang berpartisipasi dalam acara itu,” ujarnya. Menurutnya, ini bisa menjadi salah satu cara meminimalisir stigma karena dengan begitu masyarakat tahu proses seniman-seniman perempuan yang terlibat di dalamnya. Ismawati memiliki strategi yang lain. Ia menceritakan pengalamannya menyewa hotel murah agar tidak pulang malam. Ia lebih memilih menginap dan baru pulang keesokan paginya daripada dituduh pekerja seks komersil.
Selain permasalahan itu, dalam forum ini dibicarakan pula permasalahan lain seperti, kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam berorganisasi, ketidakmerataan akses, dan regenerasi seniman perempuan. Terkait yang terakhir, Rahmadyah Tria dari Forum Sudut Pandang Palu menceritakan pengalamannya. “Saya sulit sekali menemukan teman-teman perempuan di Palu yang tertarik pada kesenian. Kebanyakan masih laki-laki. Saya jadi sangat senang sekali kalau bertemu dengan teman perempuan yang punya ketertarikan sama,” ujarnya, seakan menunjukan dampak lain dari sulitnya menjadi seniman perempuan di Indonesia. Meski begitu, motivasi berkarya para seniman perempuan ini akan terus ada.

“Memang sulit menjadi seniman perempuan. Namun, jalan seni betapapun penuh semak dan belukarnya, seberapapun tak pastinya, ia akan tetap mengantarkan kita pada suatu tujuan,” ujar Ruth Marini, seniman Teater Satu Lampung yang kini bermukim di Jakarta, dalam presentasinya saat itu. [OMG]