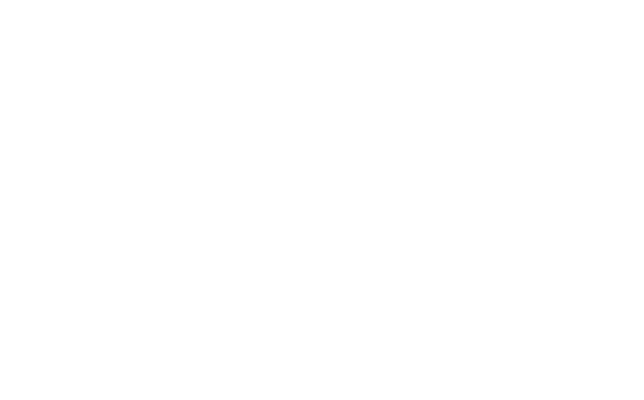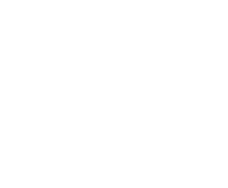Lukisan “Snake” karya Amani Ait Elasri
Creativite Indonesia memamerkan 55 karya anak dan remaja di Neha Hub, Jakarta Selatan. Para seniman muda itu merespons kekerasan seksual pada anak melalui karya seni.
Anak perempuan berambut ikal itu bertelanjang dada. Ia “terpenjara”. Kedua lengan kanan dan kirinya ditawan oleh tangan-tangan orang tak jelas siapa. Lehernya tercekik ular hijau yang memuntahkan kata-kata: “Whore”, “Nice Boobs”, “Suck My Dick” dan lainnya. Wajah si anak perempuan karut-marut. Dua matanya terserak. Pipinya berluka parut. Bibir atas-bawahnya meleyot tak keruan. Ini adalah lukisan berjudul Snake, karya Amani Ait Elasri, 11 tahun.
Di bagian bawah lukisan berdimensi 40×30 cm itu, tertulis pertanyaan: “Rapped Once?”, “Rapped Multiple Times?”. Amani, kelas 5 sekolah dasar, menyebut lukisan ini merepresentasikan rasa sakit yang terperangkap di jiwa seorang anak perempuan yang mengalami kekerasan seksual. Rasa sakit itu berpilin dengan kecemasan dan ketakutan si anak perempuan, atas persepsi masyarakat pada korban kekerasan seksual. “Wajahnya yang nggak beraturan menunjukkan bagaimana pelaku kekerasan seksual udah merusak tubuh dan jiwa korbannya,” kata Amani saat ditemui 22 Juli lalu.
Snake adalah salah satu dari tiga karya Amani yang dipampang di pameran Speak Up di Neha Hub, Cilandak, Jakarta Selatan. Perhelatan dari Creativite Indonesia itu dikuratori Gie Sanjaya, yang juga Anggota Koalisi Seni. Berlangsung selama sebulan sejak 22 Juli 2023, Speak Up memamerkan 55 karya seni dari anak-anak dan remaja yang merespons kekerasan seksual pada anak.
Gie menjelaskan tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia mendorong Creativite untuk memanfaatkan seni untuk “bersuara”. Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sejak Januari hingga akhir Mei 2023 ada 4.280 kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Adapun sejak 2018 hingga 2022, jumlah peristiwa kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia tercatat mencapai 64.591 kasus.
Merespons kondisi itu, Gie ingin lebih banyak orang -dalam hal ini anak muda- angkat bicara soal kekerasan seksual terhadap anak. Untuk itulah sebelum pameran berlangsung, Gie mengajak sejumlah sekolah dan studio lukis anak-anak, berkontribusi lewat karya seni. Total ada 187 karya yang diterima Gie, yang bentuknya tak hanya lukisan, tapi juga kolase dan puisi. “Keterbatasan ruang pamer di area terbuka membuat proses kurasi hanya meloloskan 55 karya,” ujarnya.
Seniman Dolorosa Sinaga dalam sambutannya mengatakan, pameran ini tidak semata bentuk kontribusi masyarakat untuk melawan kekerasan seksual terhadap anak. Namun juga untuk mendorong Pemerintah bertanggung jawab atas kejahatan terhadap generasi yang sedang tumbuh. “Apa yang dilakukan Gie dan anak-anak yang terlibat di sini adalah inspirasi luar biasa, dan kita bisa bergabung ke dalamnya,” kata dia.

Pengunjung pameran Speak Up menempelkan cap tangannya di lukisan karya Prajna Dewantara
Selain karya anak dan remaja, Speak Up juga menampilkan lukisan dari Prajna Dewantara. Perupa asal Bali ini adalah penyintas kekerasan seksual. Menurut Prajna, ada banyak orang yang merasakan luka yang sama dengannya, termasuk anak-anak. Sedihnya, tak banyak penyintas yang mendapat dukungan dari orang terdekatnya untuk mengambil tindakan maupun bicara soal kekerasan yang dialaminya.
Prajna yang mengalami kekerasan seksual pertamanya saat remaja, sempat terganjal stigma untuk membicarakan kejadian tersebut. “Lukisan yang saya buat dengan cap tangan dan sidik jari saya sendiri ini adalah metafora luka batin saya. Bagaimana saya diperkosa oleh orang yang saya anggap teman, dan akhirnya saya memilih meninggalkan Bali. Saya tidak bisa bicara saat itu. Tidak ada yang bisa menerima saya, termasuk orang tua sendiri,” ujar Prajna.
Luka batin korban kekerasan seksual itu juga yang mendasari Mahira, 16 tahun, dalam membuat lukisan bertajuk Pasung. Dilukis di atas kanvas dengan cat minyak, Pasung menggambarkan seorang perempuan yang tangan kanan-kirinya terikat rantai, yang tersambung ke tumpukan mata. Mata-mata itu, menurut Mahira, menggambarkan judgement masyarakat, oknum, pelaku, dan keluarga terhadap korban kekerasan seksual.
Di tempat pemasungan itu, si perempuan dikelilingi daun-daun, perdu, dan pepohonan yang menunjukkan lamanya kejadian, dan peristiwa yang terlupakan. Ada pula sebuah toilet yang menyimbolkan privasi, yang sayangnya, sudah kotor. “Aku merasa pelaku pelecehan seksual bukan manusia, karena menganggap perempuan sebatas objek,” kata Mahira, siswa kelas XI, saat ditemui selepas acara pembukaan.
Isma Savitri