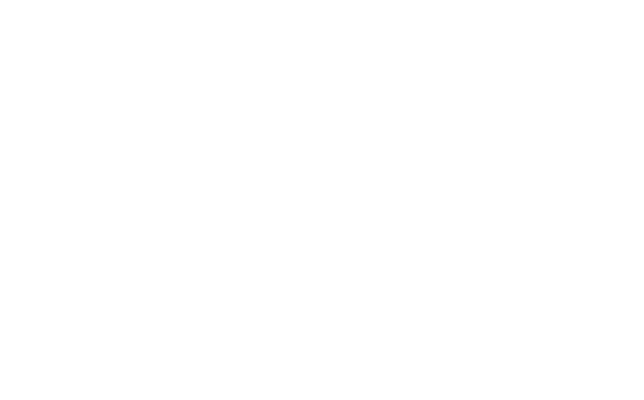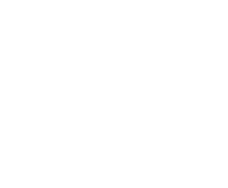Dari tahun ke tahun, angka kekerasan terhadap perempuan terus meningkat. Sementara, Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) hingga kini tak juga disahkan. Semua sektor, termasuk seni, belum menjadi ruang aman bagi perempuan. Di tengah kondisi mendesak ini, sejumlah perempuan anggota Koalisi Seni bergerak mengupayakan kesetaraan bagi perempuan melalui musik, sastra, dan kolektif seni. Tiga di antaranya adalah Kartika Jahja (Jakarta), Lily Yulianti Farid (Makassar), dan Rahmadiyah Tria Gayathri (Palu).
Sejak 2013, musisi dan aktivis kesetaraan gender Kartika Jahja mulai fokus pada isu perempuan. Meski tak mengalami secara langsung, ia mengamati cara seni dan industri musik pada khususnya, masih diskriminatif pada perempuan.

“Ketimpangan gender itu ada di depan mata. Pola pikir patriarkis membuat banyak orang menganggap itu bukan masalah, tapi setelah ditanya lagi baru sadar, oh iya, itu pelecehan ya? Itu kekerasan ya?” ujarnya.
Menurut Tika, seksisme, pelecehan, kekerasan, hingga standar kecantikan yang tak realistis masih langgeng dalam industri musik arus utama. Ia berbagi pengalamannya saat menjadi juri di salah satu kompetisi musik. Pelecehan verbal dan male gaze pada kontestan perempuan tak terhindarkan.
“Mereka melecehkan perempuan dengan komentarnya dan ngotot memilih peserta perempuan yang dianggap seksi. Pengambil keputusan masih diisi oleh gembong laki-laki yang patriarkis,” kata peraih Tokoh Seni Musik Pilihan Majalah Tempo 2009 ini.
Berangkat dari pengalaman dan keresahan akan diskriminasi terhadap perempuan, Tika membentuk sejumlah kolektif untuk mengedukasi publik tentang kekerasan gender melalui seni, musik, dan budaya pop dalam Yayasan Bersama Project, Ruang Selatan, dan Mari Jeung Rebut Kembali.
Sementara itu, di dunia sastra ada Lily Yulianti Farid, penulis sekaligus penggagas Rumata’ Art Space dan Makassar International Writers Festival (MIWF). Ia mengaku tak nyaman dengan candaan seksis yang sering dilontarkan laki-laki penulis saat berkumpul, baik secara luring maupun daring.

“Memang tidak semua ya, tapi ini kerap saya alami. Padahal mestinya sebagai penulis dan seniman, mereka ini yang harus menunjukkan sikap tidak seksis,” ucap Lily.
Menurut mantan jurnalis yang mengambil studi master bidang Gender and Development ini, masih banyak pekerjaan rumah pegiat sastra untuk menciptakan eksosistem yang setara. Masih minimnya pelatihan penulisan dan penerjemahan karya perempuan, menurut Lily, adalah beberapa penyebab yang membuat kapasitas dan kesempatan perempuan masih tertinggal dibanding laki-laki penulis. Selain itu, belum memadainya pendataan gender dalam penerbitan dan acara sastra membuat ketimpangan ini seringkali tak terlihat dan teratasi.
Identifikasi atas ketimpangan gender yang ia amati mendorong Lily menerapkan prinsip keberagaman gender dalam MIWF. Dengan itu, gagasan sastra yang muncul menjadi lebih beragam dan mewakili aneka sudut pandang. Bahkan dalam program Lintas Laut, Lily mengupayakan residensi khusus untuk perempuan penulis asal Indonesia Timur dan Australia Barat, bekerja sama dengan Centre for Stories, Perth.
“Kesadaran akan kesetaraan dan keterwakilan perempuan menjadi prinsip kerja kami. Relawan MIWF pun 80 persen perempuan. Ini pemihakan yang jelas,” tuturnya.
Lily berharap penyelenggara festival sastra pada masa mendatang menjadikan isu feminisme dan keadilan gender sebagai bagian terpadu dalam kerja dan program. Menurutnya, hal tersebut penting untuk menyudahi diskriminasi berbasis gender di dunia sastra.
Di Palu, Sulawesi Tengah, Rahmadiyah Tria Gayathri bercerita soal keberuntungannya ada di dalam Forum Sudut Pandang, kolektif seni yang menjujung nilai kesetaraan.

“Sebagai satu-satunya perempuan pendiri kolektif ini, saya memiliki privilese dalam bekerja, juga mendapat support dan perlindungan dari rekan. Saya sebagai perempuan memiliki posisi tawar setara,” ujar seniman lintas media yang akrab disapa Ama itu.
Namun, jika bicara ekosistem seni secara umum, Ama memberi rapor merah. Ia berpendapat perempuan masih sering ditempatkan pada posisi domestik dan manajerial dalam kelompok. Hal ini membuat lelaki mendominasi kesempatan untuk mengembangkan diri di bidang lain.
Bersama Forum Sudut Pandang, Ama berupaya menggunakan lensa keadilan gender dalam karyanya. Misalnya, dalam film dokumenter untuk kampanye pengesahan RUU PKS yang baru mereka rampungkan.
“Dalam proyek itu, semua kru yang bekerja adalah perempuan. Ini mungkin bisa menjadi contoh bagaimana kami mencoba mengelaborasikan kerja-kerja yang dianggap maskulin agar dikerjakan dengan kesadaran gender,” ucapnya.
Melalui masing-masing inisiatif, tiga perempuan dari tiga skena seni dan daerah yang berbeda ini punya cita-cita yang sama, yaitu terbukanya kesempatan bagi perempuan untuk mengembangkan diri. Kesadaran akan diskriminasi berbasis gender dan lenyapnya logika patriarki jadi hal penting untuk mewujudkan ekosistem seni yang setara bagi semua. (Dian Putri)