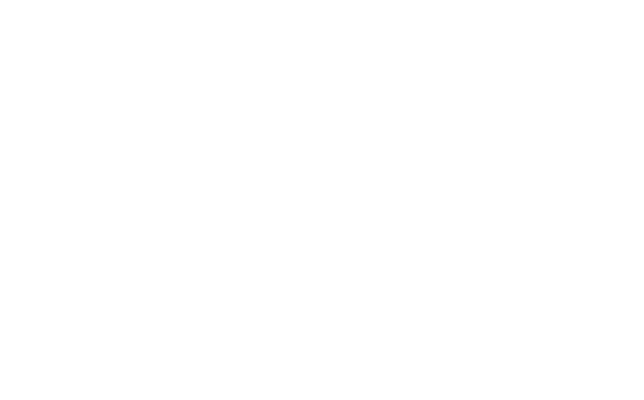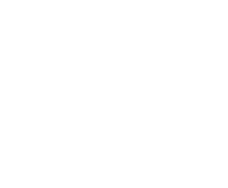Seniman dengan pemerintah biasanya tak akur. Posisi antara dua profesi ini seringnya berseberangan, hingga tak harmonis. Dengan hubungan yang seperti ini, tak heran kalau seniman jadi kurang suka bersentuhan dengan produk-produk pemerintah. Mereka jadi malas berurusan dengan sistem birokrasi.
Tetapi kini, hubungan seperti ini perlu diseimbangkan. Strategi konfrontasi yang dilakukan seniman terhadap pemerintah sudah mulai butuh ditemani oleh strategi lanjutan agar membawa perubahan yang lebih besar – khususnya bagi dunia seni dan budaya. Seniman perlu mulai untuk merambah sistem birokrasi pemerintah agar tak terus bergerak di area medioker karena memang masalah yang timbul hari ini membutuhkan lebih dari sekedar pameran atau festival seni. Perlu adanya gerakan gerilya di area yang lebih menyentuh sistem pemerintahan. Konsekuensinya, seniman perlu mulai belajar tentang sistem birokrasi pemerintah agar paham bagian mana yang bisa diperjuangkan. Konsekuensi yang mungkin terdengar asing di telinga seniman kebanyakan.
Inilah salah satu topik yang dibicarakan pada 1 november lalu. Sebenarnya, Selain tentang perlunya seniman untuk melek birokrasi, ada satu topik lainnya yang dibicarakan pada diskusi pagi itu. Sehingga, total ada dua topik pembicaraan yang diangkat pada hari itu.
Apa yang terjadi pada pagi itu adalah diskusi bertemakan Art Matters, hasil kerjasama Koalisi Seni Indonesia (KSI) dengan ruangrupa, anggota KSI yang berbentuk ruang seni di Jakarta yang sudah berdiri sejak tahun 2000. Bertempat di Tanakita Camping Ground, Sukabumi, KSI memperkenalkan kepada para pengunjung RRRECFest tentang siapa itu KSI, apa yang telah dilakukan KSI selama ini, dan apa pentingnya advokasi seni. Dengan dua pembicara, yaitu Ricky Virgana dari White Shoes and The Couples Company (WSTCC) dan Ika Vantiani dari KSI, diskusi hari itu memunculkan kesadaran baru tentang birokrasi dan advokasi seni. Sebuah kesadaran baru tentang hubungan antara seniman, pemerintah, dan masyarakat yang selama ini ternyata tak terlalu harmonis dan diam-diam saling curiga.
Advokasi Seni untuk Diri Sendiri
Ricky dan Ika bercerita tentang stigma negatif dari keluarga dan masyarakat tentang profesi seniman. Sebelum menjadi seniman profesional – Ricky kini adalah musisi profesional, sedangkan Ika adalah seniman kolase yang karyanya bertebaran dimana-mana – mereka harus berhadapan dulu dengan sikap anti-seniman dari orang tua mereka. Sebuah sikap yang timbul karena citra seniman di tahun 90an identik dengan gaya hidup yang tak sehat: mabuk, miskin, perokok berat, jarang mandi, sex bebas, obat-obatan terlarang, dan rock n roll.
“Dulu, gue ga boleh sekolah di IKJ. Soalnya orang tua tahu lah gimana sekolah seni itu. Orang tua pasti tahu gimana gaya hidup di sekolah seni. Udah gitu, berkesenian dianggap ga menghasilkan. Ga pasti,” cerita Ricky.
Ini citra yang terbentuk di tahun itu dan masih ada sampai sekarang. Bahkan, dampaknya jadi luas. Bukan saja berdampak pada citra seniman, tetapi juga pada citra seni secara keseluruhan. Anak-anak generasi yang lebih muda jadi enggan untuk terjun ke dunia seni. Kalaupun mereka mau, orang tua mereka akan melarang karena seni dianggap tak menjanjikan masa depan yang cerah. Kalau begini, jadi teringat akan cerita Irra, kepala sekolah Erudio School Of Art (ESOA), yang kabarnya karena persepsi ini harus melakukan konseling sebanyak 3-4 kali dengan pihak orang tua sebelum orang tua mengijinkan anaknya sekolah di ESOA.
“Orang tua itu ngeri ketika mendengar anaknya ingin terjun ke dunia seni. Dari kacamata mereka, anak mereka nanti akan berakhir seperti pelukis di Taman Suropati kalau belajar seni,” ceritanya di pertemuan guru seni dalam rangka membincangkan metode alternatif edukasi seni di ESOA sebulan lalu.
Persepsi seperti ini sangat disayangkan karena dunia seni hari ini sebenarnya mulai mengalami perkembangan. Atmosfer seni sekarang memungkinkan seseorang yang ingin terjun di dunia seni tak harus menjadi seniman. Banyak pilihan lain yang disediakan oleh dunia seni, seperti menjadi manajer galeri, penulis, kurator, art dealer, manajer grup musik, produser film, penulis skenario, dan lain sebagainya. Jenis-jenis profesi yang terbukti memiliki prospek masa depan yang bagus – tentu saja jika dijalankan dengan komitmen yang kuat dan dedikasi tinggi – karena perkembangan dunia seni Indonesia hari ini mulai dilirik oleh forum-forum internasional.
Bukan hanya itu saja perkembangannya. Terkait dengan mentalitas seniman, banyak seniman hari ini yang tak perlu mabuk-mabukan untuk bisa berkarya dengan baik. Hal ini karena proses kerja seniman sekarang kebanyakan lebih bersifat partisipatif. Seni hari ini tidak lagi untuk seni, tetapi untuk publik. Dengan pola pikir seperti ini, mereka harus melakukan riset mendalam terlebih dahulu sebelum bekerja membuat sebuah karya seni agar karyanya memiliki relevansi dengan permasalahan sosial di sekitar. Kegiatan riset yang tak mungkin dilakukan sambil mabuk. Jadi, sesungguhnya tak ada lagi yang perlu dikhawatirkan.
Menurut Ade Darmawan, salah satu pengawas Koalisi Seni periode 2012-2015, sekaligus salah satu pendiri ruangrupa, fenomena ini terjadi karena kurangnya penjelasan tentang proses kerja seniman kepada masyarakat. Sehingga, menurutnya, perlu adanya distribusi pengetahuan tentang apa yang sebenarnya dikerjakan oleh seniman. “Kita perlu ngasi tahu kalau ada pengalaman yang seru untuk jadi seniman. Sangat sedikit lembaga-lembaga yang ngasih liat tahapannya. Kebanyakan orang sulit untuk memilih kan karena ga tahu tahapan jadi seniman. Produksi-produksi kesenian ga pernah diterangkan dasarnya. Nanti kalau tahapannya dikasih tahu, orang-orang jadi bisa paham. Paling ga ngasih pilihan,” ungkap Ade.

Haris Azzar, koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KONTRAS), yang hadir saat itu pun melanjutkan. “Sebenarnya yang begini ini tanggungjawab seniman. Jadi, temen-temen ga cuma berkarya. Temen-temen juga punya tanggungjawab untuk merubah paradigma masyarakat tentang seniman. Bagaimana ngajak orang untuk berpartisipasi dalam seni. Ini kenapa saya seneng sama ruangrupa dan serrum karena itu yang mereka lakukan,” katanya.
Dengan begini, artinya seniman perlu melakukan advokasi seni kepada publik untuk diri mereka sendiri dimana advokasi yang dimaksud disini adalah lebih pada memberikan pemahaman, alih-alih pembelaan. “Yang pasti memang hal seperti ini butuh kesabaran karena prosesnya panjang,” kata Ika, mengingatkan.
Advokasi Seni untuk Kepentingan Bersama
Ika membuka sesi kedua dengan pernyataannya tentang independensi seniman. “Biasanya seniman itu mikirnya harus bisa melakukan semuanya sendiri. Ada pandangan kalau semua itu melawan seniman. Padahal, mungkin karena mereka ga tahu aja, jadi rasanya kayak melawan. Jadi, ada banyak sekali yang absen dalam proses berkarya kita selama ini. Absennya pemerintah, misalnya,” ungkap Ika.
Tingkat independensi seniman memang tinggi. Bahkan, cenderung berseberangan dengan yang lain, khususnya pemerintah. Dampaknya lumayan besar pada alokasi anggaran pemerintah untuk seni dan budaya di Indonesia. Maksudnya, karena kebanyakan seniman tak ingin bergantung pada pemerintah, anggaran untuk seni dan budaya jadi tak ada yang tahu lari kemana. Kalau sudah begini, maka bisa jadi praktik-praktik korupsi atas anggaran ini tumbuh subur tanpa ada yang mengawasi. Kecurigaan yang masuk akal, seperti yang diungkapkan Ricky hari itu.
“Karena kita mikir semuanya bisa kita kerjain sendiri, jadi anggaran itu ga kepake. Karena kita ga pernah tahu soal ini jadi yang nakal-nakal ini bisa tumbuh. Ternyata kampus-kampus seni dapet jatah untuk event seni dan budaya. Tapi, kita ga tahu. Ternyata seniman bisa dapet bebas fiskal, tapi kita ga sadar. Gue beruntung manajer gue, Indra Ameng, rajin ngulik jadi kita bisa dapet bebas fiskal. Kita ngulik lagi ternyata kita bisa disupport dari dinas pariwisata dan lain-lain. Sebenarnya hal-hal kayak gitu, yang kita perlu mulai pelajari sekarang,” ungkap Ricky
Istilah sederhananya adalah melek advokasi, utamanya yang bersinggungan dengan birokrasi. Bagaimana seniman mulai mempelajari haknya sebagai pelaku seni dan memperjuangkan hak tersebut kepada pemerintah karena sesungguhnya negara memiliki kewajiban dalam pengembangan seni dan budaya yang sehat di Indonesia. Dengan memperjuangkan hak seniman – tentu saja diimbangi dengan pelaksanaan kewajiban yang maksimal – seniman dapat mengedukasi pemerintah tentang kesenian. Hal ini perlu karena selama ini di kepala para birokrat tersebut, seni tak lebih dari sekedar hiburan.
“Waktu saya masih di Dewan Kesenian Jakarta, kerjasama dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, pernah meneliti soal regulasi tentang seni dan budaya sampe tingkat peraturan menteri. Ternyata tidak ada satupun regulasi yang mendukung kesenian. Contoh soal misalnya, dalam aturan ekspor impor barang. Kalau yang namanya pameran, entah itu pameran seni rupa atau festival film, begitu balik kenanya cukai impor. Pernah itu, saya ingat waktu JiFFest, kita ribet banget ngembaliin film karena kenanya cukai ekspor. Agak sinting itu. Ternyata kesenian di kepala birokrat, ga lebih dari sekedar hiburan. Ga ada itu pemikiran kalau seni juga bagian dari hidup sehari-hari masyarakat. Jadi, kita perlu mengedukasi para birokrat ini. Malah, bukan lagi mengedukasi, tapi meredukasi, ” ungkap M. Abduh Aziz, Ketua Pengurus KSI, yang juga hadir hari itu.
Masalah di bidang seni dan budaya di Indonesia memang sudah terlalu pelik untuk dibiarkan berlarut-larut. Sikap diam dan ketidakpedulian hanyalah membawa seni dan budaya Indonesia ke jurang yang lebih dalam. Lihat saja bagaimana RUU Kebudayaan dirancang. Untung saja, RUU ini batal disahkan untuk sementara ini. Kalau RUU ini benar-benar disahkan, maka akan ada pembentukan KPK (Komisi Perlindungan Kebudayaan) – tercantum dalam pasal 74 sampai 82 – yang berpotensi menjadi badan sensor kebudayaan. Satu rencana pemerintah yang aneh bin ajaib.
Maka dari itu, penting bagi para praktisi seni – bukan hanya seniman – untuk mulai mengumpulkan energi terkait hal ini. “Reformasi 16 tahun seniman ga pernah menghimpun diri untuk membangun kekuatan politik nyata. Kita belum pernah bilang ke pemerintah kalau kita ada, kita masif, kita punya banyak kontribusi. Bayangkan, anak-anak ini ga dibantu aja hidup, bagaimana kalau dibantu,” lanjut Abduh.
 Saleh Hussein, gitaris WSTCC, pun menanggapi serius ajakan ini. “Sebetulnya itu sih udah dipikirin sejak lama ya, cuma ga ada yang ngejalanin. Sebenarnya, ada rongga yang besar tuh di atas elo. Kalau elo benernya punya hak. Jadi, kalau memang hubungannya dengan pemerintah atau korporasi atau sama satu badan ya memang harusnya udah mulai dipikirkan dari dulu malah. Cuma dulu itu pola pikirnya gini. Karena kita udah jadi seniman, waktu kita udah habis untuk mikirin hal-hal yang menyangkut kesenian. Jadi, untuk ngurusin birokrasi itu peer lagi buat kita. Tapi, kalau memang kita diikutsertakan sebagai anggota untuk bertukar pikiran, untuk bagi opini soal ada rongga apalagi nih yang belum keiisi, ya ayuk,” ungkap Saleh.
Saleh Hussein, gitaris WSTCC, pun menanggapi serius ajakan ini. “Sebetulnya itu sih udah dipikirin sejak lama ya, cuma ga ada yang ngejalanin. Sebenarnya, ada rongga yang besar tuh di atas elo. Kalau elo benernya punya hak. Jadi, kalau memang hubungannya dengan pemerintah atau korporasi atau sama satu badan ya memang harusnya udah mulai dipikirkan dari dulu malah. Cuma dulu itu pola pikirnya gini. Karena kita udah jadi seniman, waktu kita udah habis untuk mikirin hal-hal yang menyangkut kesenian. Jadi, untuk ngurusin birokrasi itu peer lagi buat kita. Tapi, kalau memang kita diikutsertakan sebagai anggota untuk bertukar pikiran, untuk bagi opini soal ada rongga apalagi nih yang belum keiisi, ya ayuk,” ungkap Saleh.