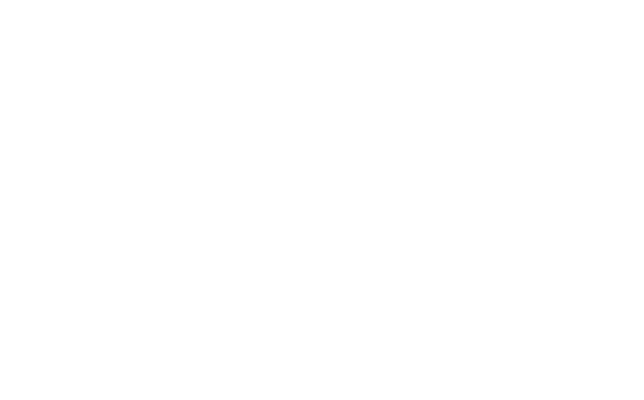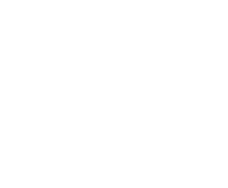Perobohan patung ikan karya I Nyoman Nuarta di Pangandaran dengan penutupan patung di klenteng Tuban seolah terikat pada sebuah narasi tentang kebangkitan kaum radikal Islam + kebodohan publik menghargai nilai senirupa. Barangkali, cetak biru narasi itu antara lain terbentuk oleh peristiwa pembongkaran patung Tiga Mojang di Bekasi, juga karya Nuarta.
Pada 19 Juni 2010, Patung Tiga Mojang dibongkar dari lokasinya di Bekasi. Persisnya, patung itu didirikan di depan gerbang perumahan Harapan Indah, Bekasi. Patung dibongkar setelah ada protes dari FPI (Front Pembela Islam). Gerombolan FPI mempersekusi karya dan acara seni bukan hal baru. Pada April 2005, FPI mengepung Museum Bank Mandiri, Jakarta, menuntut pembongkaran karya instalasi Pinkswing Park dari Agus Suwage dan Davy Linggar dan penutupan pameran CP Biennale yang menampilkan karya tersebut.
Tuntutan tersebut dengan alasan, karya tersebut mengandung pornografi dan “pornoaksi” (sebuah istilah yang ganjil, sebetulnya). Jim Supangkat bertahan tidak menutup pameran (sesuatu yang salah diberitakan pada saat itu, seolah pameran akhirnya ditutup akibat mengalah pada tekanan FPI dan publik). Tapi, pihak Museum Bank Mandiri menutup ruangan dan karya yang diributkan itu.
Jim kemudian dihujat para pekerja seni dan kurator lain karena dianggap mengalah pada FPI, sekaligus sempat mengalami disidang untuk mempertanggungjawabkan pilihan kuratorialnya. FPI sendiri, dan media massa (juga publik?), lebih sibuk pada tuntutan memperkarakan Anjasmara dan Isabel Yahya dengan tuduhan pelaku pornografi-pornoaksi.
Sesudah kemenangan moril aksi mereka dalam kasus Agus Suwage dan Anjasmara, bersamaan dengan kemenangan moril aksi FPI menghujat redaksi majalah Playboy Indonesia, Erwin Arnada saat itu, FPI tampak semakin leluasa mengobrak-abrik tatanan kehidupan berkesenian di Jakarta, Jogjakarta, Bandung, dan beberapa kota lain (khususnya, di Pulau Jawa).
Biasanya, yang jadi sasaran persekusi adalah acara-acara kesenian dan kampus yang dianggap berkaitan dengan PKI/Komunisme, mengandung pornografi, atau dianggap menghina agama Islam. Umumnya, acara-acara itu diselenggarakan di dalam ruangan. Memang rata-rata di ruang-ruang publik, tapi in-door. Patung Tiga Mojang adalah karya yang dianggap seni publik luar ruangan.
Sebentar. Benarkah patung Tiga Mojang “seni publik”? Publik yang mana? Patung itu dipesan oleh pihak perumahan Harapan Indah, Bekasi, untuk menjadi ikon perumahan mereka. Berdiri megah, setinggi 15 meter, seharga kira-kira Rp. 2,5 milyar.
Media menambahi label “berpakaian seksi” pada patung Tiga Mojang, tapi itu berlebihan. Apa seksinya? (Tentu saja, narasi berlebihan itu juga dimanfaatkan oleh FPI setempat –patung itu juga mengandung pornografi-pornoaksi). Kita bisa membayangkan, yang lebih terasa menyinggung adalah kemenjulangan dan kemewahannya.
Pameran kemewahan itu lantas menerbitkan pertanyaan lebih jauh: siapakah publik yang diharapkan menikmati karya tersebut? Para penghuni perumahan yang hidup dalam benteng pagar area perumahan mereka yang eksklusif, atau masyarakat umum di sekitar perumahan tersebut? Adakah proses pelibatan publik dalam gagasan dan pembangunan patung itu?
Sejauh data yang terkumpul tentang Patung Tiga Mojang, saya menyimpulkan bahwa karya tersebut tidaklah termasuk Seni Publik. Tentu saja, ini terkait dengan pengertian “Seni Publik” yang saya pahami. Cher Krause Knight menyigi sifat dari seni publik terletak pada “mutu dan dampak dari percakapannya dengan khalayak (…the quality and impact of its exchange with audiences).” (Knight, Public Art: theory, practice and populism, Oxford, 2008).
Bagi Knight, dalam bentuknya yang paling publik, seni mampu menggugah keterlibatan masyarakat, walau tak bisa memaksakan kesimpulan tertentu akan suatu karya. Hal ini dikukuhkan, misalnya, oleh sebuah keterangan dalam situs internet sebuah lembaga Seni Publik, Association for Public Art. Setelah menjelaskan bahwa “Seni Publik” bukanlah sebuah “bentuk”, situs itu menyaran gagasan bahwa “Seni Publik” mampu mengekspresikan nilai-nilai komunitas, meningkatkan mutu lingkungan, mengubah lanskap, meninggikan kesadaran publik, dan sebagainya (dikutip dari: associationforpublicart.org).
“Placed in public sites, this art is there for everyone, a form of collective community expression.” Dengan ditempatkan di situs-situs publik, seni hadir untuk semua, sebuah bentuk ekspresi komunitas. Demikian, bagi sebuah Seni Publik, gagasan pelibatan publik itu bisa jadi melebihi pentingnya tempat, ruang publik yang jadi lokasi kehadiran sang karya. Yang penting adalah keterlibatan publik itu sendiri, dan kehendak akan ada perubahan (transformasi) pada masyarakat lewat kehadiran sang karya.
Karya-karya fotografi-fotokopi-graffiti dari JR adalah contoh penting Seni Publik mutakhir. Pada 2008, misalnya, JR melakukan perjalanan ke Brazil, dan menyimak keterangan-keterangan para penghuni favela (pemukiman padat-kumuh) dan menemukan bahwa kaum perempuan adalah tulang punggung masyarakat di area-area favela, walaupun mereka adalah kelompok yang dipinggirkan dalam masyarakat Brazi.
Maka, JR meluncurkan proyek Women Are Heroes, sebuah aksi penciptaan yang melibatkan orang-orang di favela: potret close up wajah para perempuan penghuni favela dibesarkan begitu rupa dan ditempel di berbagai sudut dinding rumah-rumah kumuh di sana. Lanskap favela berubah, wajah-wajah perempuan memandang ke langit atau ke dunia, tajam dan memenuhi ruangan terbuka.
Karya-karya arsitektural Romo Mangun di Kali Code juga contoh lain dari Seni Publik. Lanskap dan para penghuni tertranformasi oleh ruang-ruang dan warna-warna yang dicipta di Kali Code, di situlah letak kesenian dan kepublikannya.
Patung Tiga Mojang hadir tidak dengan proses demikian. Ia hadir tanpa konteks, kecuali konteks kehumasan. Tentu, ini tidak mengurangi integritas individual Nyoman Nuarta sebagai seorang seniman. Ia menghasilkan sebuah karya yang valid dari segi kesenian. Tapi, publik, rupanya, tak menganggapnya valid.
Narasi religius yang digunakan oleh gerombolan FPI mengeruhkan dan mengalihkan pandangan kita pada masalah yang lebih penting: masalah keterlibatan publik dalam sebuah karya seni yang ditempatkan di ruang publik. Tapi, narasi religius itu justru jadi narasi kesayangan banyak pihak/kelompok saat membicarakan seni publik yang digugat atau digusur.
Apa yang terjadi di Pangandaran tak ada hubungannya sama sekali dengan konservatisme atau radikalisme Islam. Sang Bupati semata merasa perlu ada peremajaan lingkungan kotanya. Patung Nuarta di sana telah ada sejak 1987-an. Coba kita pinjam mata sang Bupati: itu patung yang bentuknya sekilas tak jelas, ganjil, tak terpahami. Mending bikin patung yang lebih jelas menggambarkan Pangandaran: patung ikan, misalnya.
Sang Bupati mengaku bahwa jika ia tahu itu karya Nyoman Nuarta yang begitu dimuliakan dalam kesenian modern internasional, ia tak akan menghancurkannya. Banyak yang mencaci Sang Bupati sebagai bodo, dan nggak ngerti seni. Tapi, apa salahnya tidak mengerti seni? Atau, mungkin lebih tepat, kita perlu bertanya: siapa yang salah jika sang Bupati itu tak paham nilai seni patung Nyoman Nuarta di kotanya?
Setelah puluhan tahun berdiri, patung Nyoman Nuarta itu perlahan kehilangan konteks kulturalnya di Pangandaran. Lagipula, tak ada yang mengupayakan agar konteks itu tidak hilang. Tak ada informasi yang gamblang dan diwariskan secara telaten tentang konteks dan nilai patung tersebut. Tak ada pendidikan seni yang memadai agar bisa membedakan mana karya seni dan mana prakarya pesanan.
Maka, masalah sesungguhnya adalah kesenjangan pemahaman akan seni itu sendiri. Jebakan memahami persoalan kesenjangan ini adalah terperangkap elitisme: “masyarakat ‘awam’ harus dididik agar lebih paham seni”. Saya mencoba lebih hati-hati. Kesenjangan itu bisa jadi mengandung aspek ketegangan-ketegangan antara seni modern dan tradisi, yang modern dengan yang tradisional, bahkan yang modern dengan yang modern itu sendiri.
Mari kita bayangkan soal ini: sebuah patung dengan harga milyaran rupiah, mengandung emas, menjulang begitu saja. Ia hadir tanpa fungsi ruang yang mudah dipahami –sebagai landmark, misalnya. Ia juga hadir tanpa makna estetika yang mudah dibaca –lebih mudah membacanya sebagai parade kemewahan. Sangat mungkin jika kehadiran massif tanpa konteks tersebut akan terasa mengintimidasi, menjajah. Menimbulkan ketegangan, perlawanan.
Ada konteks ketegangan intra-modernitas di sini. Sesama unsur kemodernan saling bersitegang. Patung yang mewakili seni modern, sekaligus juga mewakili tatanan struktur permodalan Kapitalisme (perumahan mewah di tepi metropolitan Jakarta); dan di sisi lain, ada amarah warga yang mewakili sisi gelap modernisasi, yakni peminggiran berbagai kelompok dari struktur yang sedang mendominasi. Politik identitas jadi jalan keluar yang mudah.
Ormas-ormas keagamaan menawarkan sebuah politik identitas yang lantang dan sangat artikulatif. Perasaan terserang dan tak nyaman ketika berhadapan dengan sebuah patung raksasa modern bisa segera diartikulasikan sebagai perasaan terjajah yang hanya punya jalan keluar berupa revolusi, atau, minimal, gerakan sosial mempersiapkan revolusi itu.
Dengan kata lain, ada outlet atau penyaluran bagi kemarahan itu. Retorika agama sangat membantu dalam hal ini: anti-berhala, patung dan gambar itu haram, dan patungnya mengandung pornografi!
Ketegangan intra-modernitas itu juga bisa dipandang dari segi ini: Seni rupa modern, yang bertumpu pada alur sejarah seni rupa di Eropa dan Amerika, melahirkan lembaga-lembaga seni yang memiliki kewenangan luhur menetapkan mana seni dan mana yang bukan seni. Pada saat yang sama, perkembangan masyarakat modern lewat demokratisasinya juga mencakup demokratisasi seni.
Proses ini, pada gilirannya, membuka peluang bagi perlawanan-perlawanan atau setidaknya desakralisasi (pengurangan nilai sakral, pengurangan kewenangan luhur) lembaga seni dan seni pada umumnya. Akibatnya, di masa modernisasi tahap lanjut kini, nilai luhung sebuah karya seni bisa jadi harus mengalami proses dipertanyakan ulang terus-menerus, oleh pihak-pihak yang selama dalam masa modernisasi “klasik” dianggap tak punya kewenangan mempertanyakan.
Maka, dalam konteks ini, kita bisa memandang pembongkaran patung Tiga Mojang sebagai persoalan ketegangan intra-modernitas itu. Warga sekitar patung merasa jengah, dan dengan kuat mempertanyakan makna serta nilai dari patung yang menurut keterangan lembaga-lembaga seni resmi adalah bernilai tinggi sebagai karya seni modern. Pertanyaan yang jadi aksi, unjuk rasa, dan tuntutan pembongkaran yang akhirnya dipenuhi.
Dan segi inilah yang bisa menjelaskan juga persoalan patung Nyoman Nuarta di Pangandaran yang mengalami pembongkaran lebih mutlak. Patung Tiga Mojang di Bekasi setidaknya dipindahkan saja, dan diambil alih oleh gubernur Bali. Patung di Pangandaran diratakan dengan tanah. Habis. Hancur.
Lembaga kesenian resmi (museum, kritikus, jurnal-jurnal kesenian) tak mampu merangkul warga dan publik Pangandaran. Ada yang menarik dalam berita pelantakan patung Nyoman Nuarta di Pangandaran itu. Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata, mengaku bahwa ia telah mensosialisasikan pembongkaran patung itu setahun sebelumnya. Menurutnya, ia hanya tahu bahwa itu patung pemberian perusahaan rokok Djaroem, dan hanya berkomunikasi dengan perusahaan tersebut.
Kita lihat dari pengakuan itu, bahwa patung modern yang dianggap bernilai tinggi oleh para perupa seni modern Indonesia (ini tentu saja dakuan yang belum diverifikasi) atau kritikus seni rupa Indonesia, tak lebih dimaknai sebagai benda kehumasan sebuah perusahaan rokok Indonesia oleh sang bupati.
Lebih jauh, setelah tahu bahwa patung yang telah ia bongkar adalah patung karya seorang seniman terkenal berkelas internasional, sang bupati tetap menganggap bahwa patung Nyoman Nuarta tak lagi dibutuhkan di Pangandaran.
“Kita akan bangun Patung Marlin atau bahasa Pangandarannya ikan jangilus. Kenapa ikan itu yang menjadi ikon, karena jangilus menunjukkan semangat daerah yang sedang membangun. Ikan itu agresif. Jadi bukan karena patung Pak Nyoman jelek, ini karena Pangandaran sudah punya ikon,” kata sang Bupati.
Tampak jelas, ini persoalan seni modern vs. demokratisasi (penilaian) seni, dan kegagalan pendidikan seni yang tak mampu mengenalkan nilai-nilai seni modern kepada publik seninya sendiri.
Lain lagi kasus patung di Klenteng Tuban. Ini bukan kasus seni vs. agama. Ada sengketa perdata dalam soal hak mendirikan patung itu di dalam organisasi klenteng itu sendiri. Hanya memang, lantas berdatangan para provokator yang membawa isu agama dan ras: seruan anti-Cina dan membela Islam. Kita harus membedakan dua soal ini.
Dan memang, kasus-kasus pembongkaran patung cukup banyak terjadi di era pasca-Reformasi 1998. Tempo, edisi 10 September 2017 mencatat ada limabelas kasus protes dan pembongkaran patung di berbagai daerah di Indonesia, termasuk disebut protes atas patung Zapin di Pekan Baru dan patung bawah laut di Gili, Lombok, Agustus lalu. Ada sebelas yang akhirnya benar-benar dibongkar, dengan berbagai alasan. Memang, dari telusur itu, banyak karena alasan agama.
Kasus Patung Budha di Tanjung Balai sungguh keterlaluan: dibarengi kerusuhan, dan seruan pembongkaran dari ormas Islam terhadap patung dalam lingkungan kuil. Tapi, itu sudah masalah kebebasan beragama. Kita sedang bercakap tentang masalah seni dan publik.
Dalam relasi patung dengan publik, pertanyaan yang penting adalah: siapakah “publik” yang dimaksudkan dalam praktik kesenian Indonesia? Barangkali, itu juga persoalan dasar yang kita hadapi: apakah memang ada publik seni di Indonesia, ataukah kita masih harus membangunnya?
Hal ini membutuhkan penelitian lebih dalam. ***