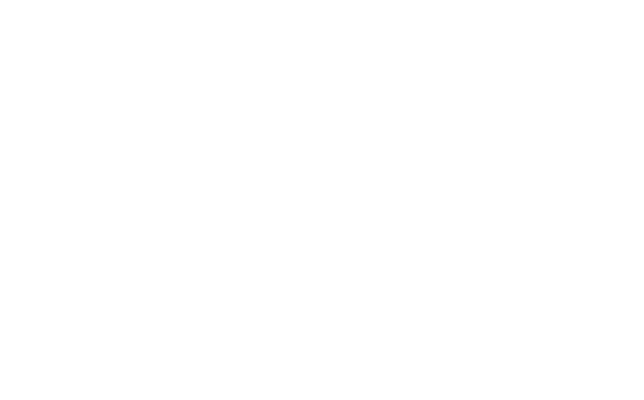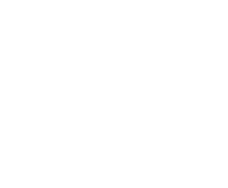Oleh Alia Swastika
Opini ini dimuat Jawa Pos pada 18 September 2021.
Dalam sejarah seni, terutama yang mengacu pada kriteria yang dianggap kanon, kita selalu dihadapkan pada kualitas-kualitas yang sifatnya monumental: entah berkaitan dengan narasi, berkaitan dengan medium dan teknik, atau sering kali juga ukuran.
Sepanjang pergulatan diskursus sejarah seni, karya-karya yang dianggap bagai karya penting, atau mahakarya, biasanya mengarah pada karya yang dihasilkan oleh seniman laki-laki pada periode waktu tertentu.
Upaya penulisan ulang sejarah seni telah dimulai dengan mempertanyakan bagaimana kriteria-kriteria mahakarya ini ditetapkan, bagaimana konteks dan konstruksi sosial yang membangun narasi karya dan sejarah dituliskan, atau bagaimana konsep gender membagi status sosial dalam periode waktu yang lalu. Dari sini, kita bisa menemukan bahwa kerja-kerja penciptaan dan pemikiran yang dilakukan oleh perempuan, dengan kompleksitas kriteria tentang “seni”, membuat nama dan karya perempuan dihilangkan dari sejarah, atau dipinggirkan posisinya sebagai “kerajinan tangan”.
Sejarah seni modern, dengan ketatnya metodologi dan epistemologi, telah membangun dua sekat yang terpisah antara seni dan kerajinan tangan (craft), dengan konstruksi akademik yang membuat seni seolah-olah berada dalam posisi yang lebih tinggi ketimbang kerajinan tangan tersebut. Kerajinan tangan lebih sering dikaitkan dengan desain, atau dengan artefak, ketimbang melihatnya sebagai hasil dari penciptaan dan kerangka pemikiran yang memiliki bingkai filosofisnya tersendiri. Proses pemisahan seni dan bukan seni ini pula yang kemudian turut berkontribusi pada penghapusan nama dan karya perempuan dalam sejarah seni, karena seringkali kerja dan hasil tangan perempuan dimasukkan kategori kerajinan dan artefak.
Di luar pembahasan atas kompleksitas kolonialisme yang kemudian menjadi salah satu poros dalam problem ini, kita bisa menyelami Kembali beberapa nama tokoh penting dalam perkembangan seni di Nusantara, dan bagaimana medium dan metode seni yang mereka dalami merupakan bagian dari kekayaan seni Indonesia yang seharusnya tidak dihilangkan dalam sejarah.
Sebut saja Mia Bustam. Jika kita mempelajari sejarah seni Indonesia modern versi kanon, nama Mia Bustam sering kali disebutkan, tetapi tidak selalu dalam kapasitasnya sebagai seniman. Acap kali Namanya disebut mengiringi nama S. Soedjojono, seniman yang sering disebut sebagai pelopor seni modern Indonesia, yang pernah menjadi suami Mia Bustam.
Lahir pada 1920, Mia meninggal pada 2011 setelah pergulatan hidupnya yang sulit. Mia membuat karya lukis, sulam atau kruistik, menggambarkan kehidupan rakyat dan rekaman sejarah kecil, yang menunjukkan semangat keberpihakannya. Ketika masuk tahanan karena peristiwa 1965, karya-karyanya hilang tak berbekas, bahkan dibakar. Ia menuliskan memoir penting Dari Kamp ke Kamp serta Soedjono dan Aku sebagai catatan atas kisah hidupnya.
Kemudian, situasi yang hamper sama terjadi pada Maryati, istri pelukis Affandi. Lahir di Jawa Barat pada 1916 dan meninggal pada 1991. Sebagaimana Mia, Maryati membuat banyak karya sulam yang sering pula dipamerkan dalam beberapa ajang seni, tetapi karya-karya semacam ini sering dianggap sebagai “karya kelas dua” yang tidak menjadi bagian dari penulisan sejarah atau koleksi penting seni Indonesia. Karya-karya Maryati banyak mengangkat lanskap, botani dan bebunga, atau narasi kehidupan perempuan.
Masmoendari, seorang pelukis tradisi damar kurung asal Gresik, mendapatkan pengakuan cukup luas ketika usianya telah mencapai 80-an tahun. Puluhan tahun hidupnya ia dedikasikan untuk mengembangkan seni damar kurung, sebuah tradisi lampion di Jawa Timur yang biasanya terjadi menjelang Ramadhan.
Dengan lukisan bergaya naif kekanakan, Masmoendari memproyeksikan kegembiraan masa kecil, lalu juga mencatat simbol-simbol yang menjadi penting sebagai bagian dari sejarah local. Pada tahun 1988, Masmoendari mendapatkan kesempatan untuk berpameran di Bentara Budaya Jakarta, dan sejak itulah karya-karyanya menjadi bagian dari dinamika seni di Indonesia. Sayangnya, setelah ia meninggal, tak banyak pelaku seni yang mengangkat kembali nama dan memamerkan karyanya.
Mangku Muriati, asal Klungkung, Bali, adalah seniman termuda dari nama-nama yang saya sebutkan di atas. Mangku Muriati berkarya dalam koridor tradisi kamasan sebagai pijakan visualnya, sebagaimana yang ia pelajari dari sang ayah. Ia kemudian mengembangkan narasi yang berbasis cerita panji atau cerita tradisi Bali, dan memberikan ruang yang lebih besar untuk membicarakan tokoh dan pemikiran perempuan seperti narasi tentang Dewi Saraswati, Shakuntala, dan lain-lain.
Sesekali, Mangku Muriati memasukkan narasi kehidupan modern yang divisualkan dengan bentuk tradisional ala kamasan, termasuk untuk membicarakan kesenjangan gender dalam strata sosial di Bali. Selain berkarya sebagai seniman, Mangku Muriati adalah seorang pemangku adat di Pura Desa, sebuah posisi yang jarang diduduki oleh perempuan.
Dari keempat nama di atas, dan melihat bagaimana masing-masing perempuan ini merupakan individu berdaya yang mempunyai spirit agensi dalam praktik keseniannya, penting bagi kita untuk terus menelusuri nama-nama lain yang berkontribusi signifikan dalam dinamika identitas kita. Para perempuan pembuat batik selama ini lebih banyak dikenang dalam diam, meskipun kita melihat bagaimana batik digembar-gemborkan sebagai simbol identitas Indonesia. Para penenun dari seluruh konteks etnis di Indonesia, semua memiliki narasi penting yang perlu kita jaga dan rawat bersama.
Mengarustamakan pemikiran perempuan dalam konteks seni berarti membongkar kriteria yang bias kelas dan bias gender dalam sejarah dan teori seni. Para perempuan yang menghasilkan bentuk-bentuk seperti sulam, tenun, keramik, perhiasan, sesuatu yang beririsan dengan praktik kehidupan sehari-hari, dalam tata kehidupan premodern mempunyai kedudukan yang penting karena hasil tangannya merupakan pendukung hidup yang signifikan, digunakan pada upacara, ritual, dan berbagai arena sosial lainnya. Rasanya, mengenang pemikiran dan semangat mereka, kita mesti melihat kembali lubang kosong dalam narasi sejarah dan memasukkan karya-karya perempuan sebagai penghormatan terhadap kontribusi mereka atas identitas kita di masa kini, juga pengorbanan mereka menjadi korban dari kekerasan politik atau penghapusan sejarah.