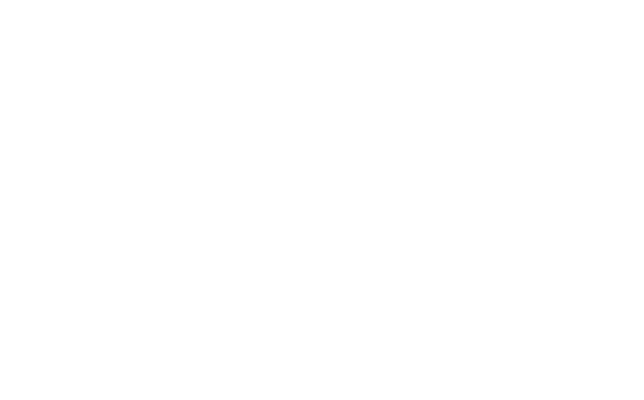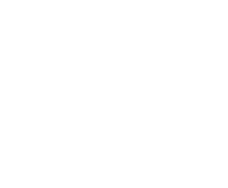Pada awal Desember 2021, dunia perfilman Indonesia kedatangan angin taifun ungu. Taifun ini datang dalam bentuk film Yuni, kisah coming of age remaja perempuan dan keterbatasan kebebasannya. Yuni, tokoh utama film ini, dilanda dilema meneruskan pendidikan ke jenjang lebih tinggi atau menikah muda. Potret realitas sosial ini bentuk kegelisahan sutradaranya, Kamila Andini, dalam melihat fenomena perkawinan anak di Indonesia. Dini, begitu ia lazim disapa, menceritakannya dalam wawancara daring menjelang akhir 2021.
Yuni membuat saya tertarik mengeksplorasi cara Dini mempraktikkan kebebasan berkesenian dalam proses penciptaan di baliknya, khususnya hak berkarya tanpa sensor dan intimidasi serta hak ikut serta dalam kehidupan kebudayaan. Hak pertama adalah prasyarat agar seniman dapat berkarya sesuai idealismenya. Sementara itu, hak kedua memberi ruang pada kelompok rentan – termasuk perempuan kelas pekerja – punya hak setara untuk berkebudayaan, salah satunya lewat seni. Kalau kata karakter Suci Cute dalam film Yuni: preedom abis!
Preedom untuk berkarya sesuai keyakinan
Sebagai orang yang konsisten menggambarkan berbagai isu perempuan di karya-karyanya, Dini sadar isu perkawinan anak bukan hal baru di Indonesia. Riset pada 2018 menunjukkan 1 dari 9 perempuan di Indonesia menikah di bawah umur 18 tahun dan membuat Indonesia 1 dari 10 negara dengan fenomena perkawinan anak tertinggi di dunia.
Cerita film Yuni telah merasuki benak Dini sejak 2016. Dini terinspirasi cerita seorang ibu yang menceritakan pengalaman anaknya menikah muda. Cerita ini membawanya melakukan riset di beberapa daerah di Indonesia dan pertanyaan-pertanyaan mulai menggunung di benaknya, “Jika hidup di ruang berbeda dengan ruang hidup saya saat ini, apakah saya bisa menjadi saya yang sekarang? Apakah saya memiliki keberanian melawan konflik struktural?”
View this post on Instagram
Suara-suara itu tidak bisa lepas dari pemikirannya, hingga ia yakin ini kisah yang menjadi inti karya berikutnya. Sebagai ibu dari dua anak perempuan, ia ingin perempuan dapat membangun ruang untuk diri sendiri dan memiliki suara sendiri. Untuk itu, karya dengan pendekatan female gaze yang memihak remaja perempuan dibutuhkan.
Namun, menjadi remaja perempuan merupakan pengalaman yang kompleks. Rasa ingin tahu serta eksplorasi fisik dan mental yang kerap dilakukan remaja cenderung tabu diperlihatkan dalam norma masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, Dini berkata dengan penuh keyakinan, “Saya belajar dari Yuni untuk tidak terbiasa terpaksa menyenangkan orang lain.”
Dini pun belajar dari karakter Yuni bahwa menjadi people pleaser adalah cara termudah menutup ruang bagi diri sendiri. Maka, ia pun berpegang teguh pada idealisme yang dimilikinya pada film ini. Sejak awal, ia ingin jujur dan terbuka pada seluruh anggota tim Yuni dengan membagikan visi dan misinya pada mitra, kru, dan aktor film ini. Para pemain memiliki latar belakang berbeda-beda sehingga perbedaan pendapat tak mungkin dihindari, namun tim Yuni dapat mengelolanya.
Saya bertanya pada Dini, adakah keraguan dalam membuat karya yang jujur dan progresif? Ia tertawa lalu menjawab, “Membuat film Yuni rasanya seperti ganti baju di depan semua orang, tapi kolektivitas dan keberanian kita di sini untuk hal yang baik.”
Dini mengaku awalnya ragu membawa topik ini, namun masyarakat lokal yang merespon visinya dengan positif memberikannya keberanian. Ia pun semakin yakin dengan pemikirannya bahwa opini beragam dan keberagaman perlu diperlihatkan kepada masyarakat Indonesia yang juga beragam.
Idealisme Dini menuntunnya melawan keraguan dan teguh dalam ekspresi keseniannya. Ketika saya menyaksikan Yuni dan melihat adegan-adegan yang berpotensi memicu kontroversi – seperti Yuni menari di bawah lampu neon klub malam dengan bahagia atau aksi Yuni yang penasaran dengan konsep orgasme – layar memancarkan kejujuran, kekuatan, dan katarsis yang patut dirayakan semua penonton. Ini merupakan buah manis perjuangan seniman dalam membuat ruang untuk diri sendiri dan karyanya dalam ekosistem kesenian.
Preedom untuk mengalami dan menikmati seni
Sebagai sutradara yang memiliki gelar Sarjana Sosiologi dari Deakin University, Australia, Dini gemar membuat film secara kolektif dengan masyarakat lokal. Menurut Dini, ide merupakan benih, ia membutuhkan tanah yang tepat untuk tumbuh. Komunitas lokal merupakan tanah dan hujan yang menentukan mekar tidaknya suatu karya.
Komunitas lokal pun menjadi mitra riset dan pengembangan naskah film Yuni. Selain itu, kru dan para pemain diharuskan tinggal bersama masyarakat lokal dan mengikuti proses pembelajaran bahasa Jawa-Serang dengan pelatih dialek. Proses ini membantu mendekatkan film Yuni dengan realitas masyarakat yang ditampilkan. Realitas ini dipertebal lagi dengan ikut sertanya aktor dari Serang, seperti Nazla Thoyib sebagai pemeran Nenek.
Selain berupaya menyajikan konteks lokal senyata mungkin, produksi film Yuni juga berperspektif feminis. Dini menyaksikan dan menghadapi betapa sulitnya perempuan untuk dapat terus berpartisipasi dalam seni. Titik tersulit bagi Dini dalam bertahan di industri perfilman adalah ketika ia menikah dan memiliki dua anak. Ini juga terjadi pada rekan perempuan lainnya. Sebab, cara kerja industri perfilman memang rentan bagi perempuan: tak tentunya jam kerja, tidak kondusifnya ruang, juga nafas pendek proyek yang selalu berpindah lokasi. Sehingga, lebih banyak laki-laki bertahan di dalam industri. Dini merasa sistem yang ada membuatnya kesulitan mengejar kebutuhan industri.
Namun, ia menolak menyerah. Dini merasa sebagai sutradara perempuan, ia harus menemukan ritme dan cara produksinya sendiri. Maka, ia membangun sistem produksi yang ramah perempuan dan anak. Yuni memakai jam kerja lebih teratur ketimbang lazimnya produksi film, sehingga jadi tempat ramah bagi para pekerja yang juga ibu. Dini juga memastikan isu perempuan bersirkulasi di lingkungan hulu film Yuni pada kru laki-laki sebelum mencapai hilir. Semua kru wajib menandatangani klausula Anti Kekerasan Seksual, karena kekerasan seksual tidak ditolerir. Dengan mengamankan ruang dan memperluas akses bagi pekerja perempuan, Dini berharap keadilan gender dapat diwujudkan di ruang produksinya.
Dengan memberikan posisi yang setara bagi masyarakat lokal dan memudahkan perempuan ikut andil dalam produksi film Yuni, Dini serius memastikan berbagai kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan kebudayaan. Ini contoh baik yang patut diterapkan untuk produksi-produksi kesenian lainnya, karena seharusnya setiap orang memiliki kesempatan setara dalam memproduksi dan menikmati seni.
Meneruskan Preedom Melalui Film Yuni
Pada awalnya, Dini terkejut pada besarnya animo masyarakat terhadap film Yuni. Ia mengira hanya segelintir masyarakat dapat menerima film Yuni. Pada saat bersamaan, Dini pun sadar satu film tak bisa jadi solusi untuk masalah masyarakat yang kompleks. Sebagai seniman, ia juga merasa tidak mungkin terus mengorientasikan karya pada satu isu spesifik.
Saat itu, Dini sadar filmnya berpotensi menjadi riak besar dalam menggambarkan kelamnya efek pernikahan anak di Indonesia. Untuk menggulirkan langkah lebih besar lagi, ia menjalin sinergi dengan pihak-pihak yang memiliki kapasitas mengadvokasi isu tersebut.
Hasilnya, Yuni jadi medium kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (#16HAKTP) bersama Magdalene, Plan Indonesia, Rutgers, dan Hivos dalam pencegahan perkawinan anak. Film Yuni diputar di berbagai tempat di Indonesia, termasuk bioskop mainstream maupun independen. Diskusi-diskusi mengenai nilai-nilai film Yuni pun digelar di berbagai pemutaran. Selain itu, bergulir pembacaan surat-surat penonton Yuni soal pengalaman buruknya tentang perkawinan anak oleh pemain film tersebut, yang diunggah ke media sosial dengan tagar #YUNITE.
Dini berharap setelah film ini, kesadaran masyarakat tentang isu kompleks ini meningkat. Hari ini, anak perempuan hidup di dunia yang lebih luas dan terhubung. Kemajuan teknologi internet membuat remaja perempuan terpapar segala kemungkinan di masa depannya di luar pernikahan. Menurutnya, perlu dua orang yang utuh untuk masuk ke dalam suatu pernikahan. Sebagai ibu dan seniman, ia mengajak remaja perempuan di mana pun berada untuk mengenal diri sendiri dan potensinya sebelum masuk ke dalam bahtera pernikahan. (Aicha Grade Rebecca)
Foto Yuni: Dokumentasi Fourcolours Film/StarVision/Akanga Film Asia/Manny Films